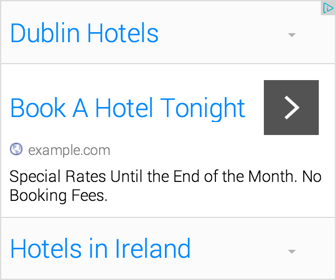Oleh: Fridolin Denri Bria
Saya tidak menulis ini sekadar untuk membuka luka lama, tetapi untuk mengingatkan bahwa keadilan tidak berumur pendek. Nama Ferdy Sambo mungkin sudah jarang muncul lagi di televisi, tetapi memori tentang kasus itu tidak boleh kita kubur hanya karena berita baru terus berdatangan. Sebab apa yang terjadi saat itu bukan hanya soal satu nyawa yang direnggut, melainkan tentang bagaimana kekuasan bisa berubah bentuk menjadi topeng yang menakutkan.
Peristiwa yang mengguncang itu terjadi pada 8 Juli 2022, di rumah dinas seorang jenderal polisi. Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang kita kenal sebagai Brigadir Y ini tewas bukan ditangan musuh negara, tapi di tangan orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Awalnya publik disuguhi cerita baku tembak, lengkap dengan drama ala sinetron versi aparat. Tapi seiring penyidikan berjalan, lapisan demi lapisan kebohongan mulai terbuka. Ada rekayasa kronologi. Ada bukti yang dihilangkan. CCTV mendadak hilang arah. Semua tampak seperti panggung sandiwara, hanya saja yang jadi korban bukan perasaan, melainkan kebenaran.
Setelah tekanan publik memuncak, barulah fakta hukum berdiri tegak. Pengadilan mengatakan bahwa ini bukan kecelakan, bukan salah paham, melainkan pembunuhan yang direncanakan. Pada Februari 2023, putusan pertama dijatuhkan yaitu hukuman mati untuk Ferdy Sambo. Namun proses hukum di Mahkamah Agung kemudian mengubahnya menjadi penjara seumur hidup. Banyak yang lega, sebagian masih ragu. Tetapi satu hal pasti: negara dipaksa bercermin.
Kalau kita tarik garis lebih dalam, sebenarnya filsuf Jean-Jacques Rousseau sudah lama mengingatkan bahaya semacam ini. Ia katakan, kekuasan itu bukan datang dari langit, melainkan titipan dari rakyat. Kita menyerahkan sebagian kebebasan agar negara melindungi kita. Itu yang disebut kontrak sosial. Namun apa jadinya kalau yang diberi wewenang malah merasa dirinya kebal dari hukum? Kontrak itu pun sobek, dan rakyat hanya jadi penonton.
Bagi saya, Sambo bukan hanya nama pelaku. Ia representasi dari satu pertanyaan besar: seberapa kuat hukum kita ketika melanggarnya adalah mereka yang memakai seragam penegak hukum itu sendiri? Di titik inilah kepercayaan publik dipertaruhkan. Kalau aparat bisa memanipulasi kenyataan seenaknya, lalu untuk apa rakyat percaya lagi? Kadang saya bertanya dalam hati: Apakah negara ini berdiri di atas aturan, atau di atas siapa yang paling berkuasa?
Kalau hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, maka kita tidak sedang hidup di negara hukum, melainkan hutan belantara yang rapi dikemas pakai seragam. Yang membuat saya sedikit lega dari kasus ini adalah kenyataan bahwa publik tidak diam. Suara masyarakat, tekanan media, dan keberanian keluarga korban ikut membuka pintu kebenaran yang sempat dikunci rapat.
Artinya bahwa rakyat masih punya daya. Kepercayaan terhadap sistem memang retak, tapi bukan berarti harapan sudah patah. Justru dari kasus inilah kita bisa belajar bahwa keadilan tidak datang dengan sendirinya yang mana ia harus dipanggil dengan suara yang keras dan dijaga agar tidak kabur kembali.
Namun dalam menyelesaikan perkara lewat vonis pengadilan saja tidak cukup bila kita membiarkan pola yang sama tetap hidup dibelakang layar. Hukum tidak akan pernah berdiri tegak jika proses penegakannya masih penuh kamar gelap. Yang penting dari hukuman adalah mencega agar tragedi semacam ini tidak punya tempat untuk terulang. Itu artinya urusan keadilan tidak boleh hanya diserahkan kepada meja sidang, tetapi juga pada sistem yang mengawasi para pemilik wewenang agar tidak merasa dirinya seperti penguasa tunggal.
Kita butuh mekanisme pengawasan yang tidak bisa dinegosiasi oleh jabatan. Tidak boleh ada lagi kasus yang diselesaikan secara internal lalu menguap tanpa jejak. Investigasi semestinya dibuka selebar-lebarnya, bahkan kalau perlu libatkan pihak independen di luar institusi agar tidak terjadi konflik kepentingan. Masyarakat berhak tahu bagaimana fakta dicari, bukan hanya diberi hasil akhir yang sudah jadi.
Selain itu, pendidikan bagi aparat tidak boleh hanya soal kemampuan teknis. Orang yang bisa menembak belum tentu tahu kapan harus menahan pelatuknya. Keberanian menggunakan senjata harus seimbang dengan keberanian menjaga nurani. Etika dan moral bukan pelengkap, melainkan pondasi. Sebab tanpa itu, hukum hanya menjadi kostum dipakai ketika perlu, dilepas ketika menghalangi.
Peran media dan masyarakat sipil juga tidak boleh dipandang sebagai gangguan. Justru di tengah sistem yang kadang malas bercermin, wartawan dan warganetlah yang menjadi cermin bergerak. Kalau dulu suara rakyat bisa memaksa penguasa minta maaf, sekarang semestinya suara itu bisa memaksa sistem memperbaiki dirinya sendiri. Demokrasi tidak hidup dari pemilu saja, ia hidup dari kritik yang jujur dan keberanian menolak dibodohi.
Hal kecil seperti rekaman CCTV atau laporan digital tidak boleh lagi dibiarkan hilang begitu saja seolah angin meniupnya. Teknologi mestinya jadi penjaga kebenaran, bukan korban yang pertama dibungkam. Standar penyimpanan bukti harus diperketat, dan orang yang berani membocorkan ketidakadilan harus dilindungi, bukan dikorbankan. Saya percaya, Nusa Tenggara Timur pun tidak kebal dari kasus seperti ini. Jangan tunggu kejadian besar baru kita bicara. Lebih baik kita belajar dari tragedi orang lain sebelum kita menanggungnya sendiri. Biar aparat tahu, jabatan tidak bisa dipakai sebagai selimut untuk menyembunyikan kesalahan. Dan biar rakyat sadar, diam bukanlah sikap bijak, tetapi bentuk pembiaran.
Oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan satu hal: keadilan tidak boleh berhenti pada satu putusan, ia harus hidup dalam kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita mau negeri ini jadi tempat yang aman dan adil, bukan hanya dibaliho dan pidato, maka kita semua harus ikut menjaga pintu agar kekuasaan tidak leluasa menyelinap lewat jalan belakang. Seragam boleh membungkus tubuh, tapi jangan sampai membungkam hati.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira Kupang