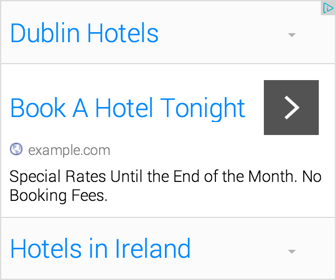Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
(sebuah catatan di balik kericuhan APEBUAN CUP perspektif filsafat estetika)
Turnamen sepak bola di Flores Timur kembali bergemuruh, bukan oleh sorak kemenangan, melainkan oleh riuh kericuhan yang pecah pada Minggu, 24 Agustus 2025. Dalam emosi memuncak, tampak para suporter menyeruak ke lapangan bak para jagoan yang turun dari khayangan, membawa bukan hanya amarah, tetapi juga simbol-simbol kegelisahan sosial yang tak terucap. Apebuan Cup 2025 pun seolah ternoda.
Namun dalam pandangan estetika filsafat, kericuhan ini bukan sekadar kekacauan. Ia adalah panggilan untuk merenung, untuk membaca ulang makna kompetisi sebagai cermin jiwa kolektif. Di tengah sorotan kamera dan viralnya video yang beredar pada Minggu, 24 Agustus 2025 ini, kita diajak menyelami bahwa di balik setiap benturan, ada narasi yang menunggu untuk ditafsirkan: tentang identitas, harapan, dan ruang publik yang sedang mencari bentuknya kembali.
Sepak bola, dalam konteks budaya lokal, bukan hanya olahraga, melainkan ritual kolektif yang menyatukan tubuh, emosi, identitas, dan harapan masyarakat. Ia adalah panggung tempat estetika gerak, strategi, dan solidaritas komunitas dipertunjukkan secara publik. Namun, ketika kericuhan muncul, kita menyaksikan bagaimana ruang yang seharusnya menjadi arena keindahan dan kebersamaan berubah menjadi medan konflik dan ekspresi destruktif.
Dalam filsafat estetik, keindahan tidak selalu hadir dalam bentuk yang harmonis dan menyenangkan. Ada pula keindahan yang lahir dari ketegangan, dari retakan dalam tatanan yang mapan, dari ekspresi yang mengguncang kenyamanan. Kericuhan dalam sepak bola dapat dibaca sebagai bentuk “estetika gangguan” yakni ekspresi yang mengusik, yang memaksa kita untuk melihat lebih dalam ke akar persoalan sosial, psikologis, dan kultural yang melatarbelakanginya.
Mengapa gairah kolektif berubah menjadi agresi? Apakah ada ketimpangan dalam sistem penyelenggaraan, representasi, atau akses terhadap ruang publik? Apakah simbol-simbol kompetisi telah melampaui batas sportivitas dan menjadi alat eksklusivisme atau dominasi?
Filsafat estetik mengajak kita untuk tidak hanya menilai bentuk luar dari suatu peristiwa, tetapi juga memahami intensi, konteks, dan resonansi batinnya. Dalam hal ini, kericuhan bukan hanya soal perilaku menyimpang, tetapi juga cerminan dari kegelisahan sosial yang belum menemukan saluran ekspresi yang sehat dan konstruktif. Akan hal ini, jalan keluarnya bukan sekadar penertiban atau pengamanan, melainkan rekonstruksi ruang publik sebagai arena pembentukan karakter, dialog, dan refleksi nilai.
Secara filosofis, kita dapat merujuk pada gagasan Martin Buber tentang “Aku-Kau” sebagai relasi yang autentik dan saling menghargai. Dalam konteks turnamen, relasi antara pemain, penonton, panitia, dan masyarakat luas harus dibangun bukan sebagai “Aku-Itu” yang objektif dan instrumental, melainkan sebagai “Aku-Kau” yang dialogis dan penuh empati. Sepak bola harus menjadi medium perjumpaan, bukan pemisahan. Di sisi lain, Hannah Arendt mengingatkan kita bahwa ruang publik adalah tempat munculnya tindakan dan wacana yang membentuk dunia bersama. Jika kericuhan terjadi, itu berarti ruang publik belum cukup mendukung munculnya tindakan yang bermakna dan wacana yang membebaskan.
Dari sisi filsafat estetika, saya hendak menawarkan solusi yang bukan sekadar perbaikan teknis, melainkan sebuah rekonstruksi makna: merancang ulang turnamen sebagai peristiwa estetik yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan membentuk jiwa. Turnamen harus menjadi ruang pembelajaran nilai dan karakter, yang terintegrasi sejak tahap seleksi pemain hingga penyusunan jadwal dan sistem kompetisi. Di dalamnya, setiap langkah bukan sekadar prosedur, melainkan proses pembentukan manusia yang sportif, reflektif, dan bertanggung jawab.
Dari sisi ini boleh dikatakan bahwa turnamen dapat menjadi wadah refleksi kolektif melalui forum-forum dialog sebelum dan sesudah pertandingan, melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan penyelenggara dalam percakapan yang jujur dan membangun. Simbol-simbol lokal yang mengangkat nilai kebersamaan, keberagaman, dan spiritualitas perlu diperkuat, agar kompetisi berubah menjadi perayaan identitas bersama. Sportivitas, perdamaian, dan harapan akan kebaikan bersama yang menggembirakan, menjadikan setiap pertandingan bukan hanya ajang adu keterampilan, tetapi juga panggung pembentukan peradaban.
Dengan pendekatan estetik dan filosofis, kericuhan tak lagi dipandang sebagai bayang-bayang ancaman, melainkan sebagai nyala obor yang mengundang kita untuk menata ulang makna kebersamaan. Ia menjadi gema dari kedalaman jiwa kolektif, panggilan untuk membangun ruang publik yang lebih manusiawi, tempat di mana sorak tak menenggelamkan nurani, dan kompetisi tak menghapus refleksi. Di sana, setiap benturan bukan sekadar konflik, melainkan peluang untuk menyulam kembali tenun sosial yang retak, dengan benang-benang empati, kesadaran, dan harapan.
Sepak bola di Flores Timur, dengan segala riak dan gelombangnya, menjelma menjadi cermin yang memantulkan wajah masyarakat, sekaligus laboratorium tempat nilai-nilai luhur diuji dan dibentuk. Di lapangan yang berdebu itu, kita melihat bukan hanya permainan, tetapi proses pematangan emosional, sosial, dan spiritual. Di antara sorakan dan peluit, tumbuhlah benih-benih kebijaksanaan: bahwa sportivitas bukan sekadar aturan, melainkan sikap hidup; bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menjaga martabat, merawat keberagaman, dan menyalakan api persaudaraan yang tak lekang oleh waktu.***
Penulis adalah Pengajar di Sekolah Tinggi Pastoral (Stipar) Ende