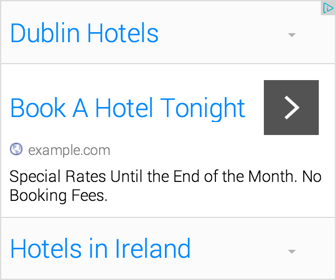Setiap perjalanan hidup manusia selalu meninggalkan jejak, entah berupa luka, tawa, atau doa yang pelan-pelan merangkai dirinya menjadi cerita. Wisuda bagi saya bukan sekadar akhir dari sebuah proses akademik, melainkan sebuah tanda kecil dari perjalanan panjang yang dituntun oleh tangan-tangan kasih Tuhan dan orang-orang terkasih.
Di balik toga dan ijazah, ada kerja keras yang kadang penuh air mata, ada doa yang tidak pernah putus dari orang tua, ada dukungan sahabat, dan ada senyum polos anak-anak yang mengingatkan bahwa hidup selalu layak disyukuri. Maka, ketika hari syukur itu tiba di Sonaf Maneka, saya menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah ditentukan oleh besar kecilnya pesta, melainkan oleh kehadiran yang tulus dan doa yang sederhana.
Kemarin sore, langit Kupang mulai memudar dalam semburat oranye yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Angin sore membawa aroma tanah kering bercampur wangi masakan dari dapur yang sibuk sejak siang hari. Di halaman Panti Asuhan Sonaf Maneka, kursi-kursi plastik ditata sederhana, altar kecil dipersiapkan dengan lilin dan bunga, dan anak-anak panti berlarian riang, menyambut tamu yang mulai berdatangan.
Tidak ada hiasan berlebihan, tidak ada kemegahan yang dipaksakan. Namun, ada sesuatu yang membuat suasana terasa lengkap: cinta yang bekerja diam-diam dalam setiap tangan yang menata kursi, dalam setiap senyum yang menyambut, dalam setiap doa yang terucap. Malam itu bukan sekadar pesta, melainkan sebuah Misa Syukur, sebuah perayaan yang mengembalikan seluruh perjalanan ini ke dalam tangan Tuhan.
Beberapa jam sebelum misa dimulai, saya sempat ditanya oleh Bapa Ucha. Dengan nada santai, tapi penuh makna, ia berkata: “Beritahu ka Erik mottonya apa?”
Pertanyaan itu sederhana, tapi seakan mengetuk pintu batin saya. Tanpa sempat berpikir panjang, mulut saya menjawab spontan: “Sederhana jalannya, besar artinya.” Saya sendiri sempat terdiam. Kata-kata itu muncul begitu saja, seolah tidak saya ciptakan, melainkan diberikan. Baru setelahnya saya sadar, mungkin seluruh perjalanan yang saya tempuh memang sedang berbicara lewat kalimat itu.
Ketika misa dimulai, suasana berubah hening. Lagu pembuka yang dinyanyikan anak-anak panti mengalun polos, tanpa iringan alat musik yang megah, namun justru menyentuh hati dengan kejujuran yang murni.
Imam, RD. Mantho Bulu Manu, berdiri di depan altar sederhana, memimpin perayaan dengan doa yang mengalir penuh penghayatan. Bacaan Kitab Suci malam itu terdengar begitu dekat, seperti sedang berbicara langsung kepada saya: tentang perjalanan, ketekunan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang jalan hidup.
Dalam homilinya, Romo menyinggung arti sebuah syukur, bahwa syukur bukanlah milik orang yang hidup tanpa luka, melainkan milik mereka yang berani mengakui luka, namun tetap melihat kasih Tuhan yang bekerja di dalamnya. Jangan menjadi musuh dalam selimut. Sebab sering kali yang merusak bukanlah badai dari luar, melainkan bisikan kecil dari hati yang iri dan enggan bersyukur. Syukur sejati menuntut kejujuran untuk mengalahkan ego, agar kita tidak jatuh menjadi penghalang bagi berkat orang lain.
Dan ketika syukur itu hidup, luka pun berubah menjadi jalan terang yang menyatukan, bukan memisahkan. Kata-kata itu membuat hati saya bergetar. Saya teringat malam-malam begadang di depan buku, rasa putus asa menghadapi tugas-tugas yang seakan tidak ada habisnya, hingga saat-saat ketika saya nyaris menyerah. Namun, dalam setiap titik lemah itu, selalu ada sesuatu atau seseorang yang hadir memberi kekuatan: doa Bapa dan Mama, dukungan saudara, sapaan sahabat, bahkan senyum polos anak-anak panti yang mengingatkan saya bahwa hidup tetap berharga meski jalannya penuh kerikil.
Puncak misa tiba saat roti dan anggur diangkat. Hati saya seakan ditarik mundur menelusuri jejak perjalanan. Ada kesadaran yang tajam bahwa saya tidak pernah berjalan sendirian. Ada tangan-tangan tak terlihat yang selalu menopang: tangan orang tua yang tidak lelah berdoa, tangan sahabat yang setia menemani, tangan para dosen yang dengan keras menuntut, namun demi kebaikan. Dalam keheningan itu, saya merasakan sesuatu yang lebih besar daripada diri saya sendiri, yakni sebuah cinta yang menuntun, bahkan ketika saya tidak menyadarinya.
Misa diakhiri dengan berkat penutup. Semua orang berdiri, saling memberi salam damai, dan senyum mengalir dari satu wajah ke wajah lain. Namun bagi saya, misa itu bukanlah akhir. Ia justru menjadi awal dari sebuah bab baru: bab syukur yang harus saya hidupi, bukan hanya diucapkan. Setelah misa, acara keluarga sederhana dimulai. Meja makan diruang tamu sudah dipenuhi dengan hidangan yang disiapkan sejak pagi. Nasi, sayur, telur puyuh, ayam goreng, daging babi dan es serut tersaji tanpa kemewahan, namun setiap suapannya terasa seperti hadiah.
Gelas-gelas beradu pelan, percakapan hangat mulai memenuhi udara, dan tawa mengalir dari sudut ke sudut. Tidak ada panggung, Tidak ada hingar-bingar, hanya musik lembut yang mengalun pelan mengiringi makan malam, seakan menjadi latar doa syukur yang tidak terucapkan. Namun justru di sanalah kebahagiaan tumbuh, dari kesahajaan yang tidak dibuat-buat.
Saya memperhatikan sekeliling. Wajah Bapa dan Mama saya tampak berseri, meski saya tahu tubuh mereka lelah. Ada kebanggaan yang mereka sembunyikan di balik senyum, ada doa yang mereka tidak ucapkan keras-keras, tapi saya tahu terus naik ke langit. Saya menatap saudara-saudara, sahabat-sahabat, juga anak-anak panti yang berlarian sambil sesekali ikut bernyanyi. Malam itu, saya belajar bahwa kebahagiaan tidak pernah lahir dari pesta besar, melainkan dari kebersamaan yang sederhana, dari wajah-wajah yang hadir dengan tulus.
Jam terus bergerak. Dari satu hidangan ke hidangan lain, dari cerita lama ke canda yang baru, waktu berjalan tanpa terasa. Anak-anak panti yang tadi riuh mulai kelelahan; ada yang tertidur di kursi, ada yang bersandar di bahu kakaknya, namun senyum tetap terukir di wajah mereka. Para tamu perlahan pamit, tapi tawa masih tersisa di udara. Hingga akhirnya, jarum jam mendekati pukul dua belas malam. Acara pun perlahan ditutup, menyisakan kehangatan yang tidak akan cepat hilang.
Saya berdiri di halaman Sonaf Maneka, menatap kursi-kursi kosong yang beberapa jam sebelumnya dipenuhi wajah penuh doa dan tawa. Angin malam menyapa lembut, dan bintang-bintang bertaburan di langit. Dalam hati, saya merasa Tuhan benar-benar hadir di malam itu, tidak dalam wujud besar, tapi dalam senyum, tawa, dan cinta yang saling dibagi.
Dan akhirnya, dari hati yang paling dalam, saya hanya bisa mengucapkan: Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan, yang menuntun setiap langkah saya dengan setia. Terima kasih kepada Bapa dan Mama, yang doa dan pengorbanannya adalah fondasi dari perjalanan ini. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, para dosen, sahabat-sahabat, dan semua yang hadir dalam Misa Syukur serta kebersamaan hingga tengah malam. Terima kasih kepada anak-anak panti, yang dengan polos mengajarkan arti sukacita yang sederhana. Terima kasih juga kepada rumah ini, Sonaf Maneka, yang dalam kesederhanaannya telah menjadi altar kasih, doa, dan sukacita.
Malam itu mengajarkan saya sebuah kebenaran sederhana: bahwa hidup, ketika dijalani dengan rendah hati, akan selalu sederhana jalannya, tetapi besar artinya. Kesederhanaan membuat kita mampu melihat keindahan dalam hal-hal kecil yang sering terabaikan. Dari tawa yang pecah di meja makan hingga doa yang lirih diucapkan, semuanya menjadi jejak kasih yang tidak ternilai. Dan saya belajar, bahwa makna hidup bukan diukur dari seberapa tinggi kita berdiri, melainkan dari seberapa dalam kita mampu berterima kasih.
Oleh: Patrison Benefaciendo Bulu Manu, (Alumnus Fakultas Filsafat Unwira Kupang).