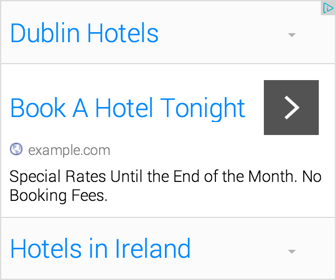Berita tentang penyitaan buku oleh Polda Jawa Timur — sebelas judul dari tangan tersangka demonstran yang disebut mengandung “paham komunis dan anarkis” — mengingatkan kita kembali pada topik lama namun selalu relevan: bagaimana negara memandang ide yang berbeda dan batas-batas yang ia tarik antara keamanan publik dan kebebasan intelektual. Peristiwa ini bukan sekadar aksi penegakan hukum yang teknis; ia adalah simbol, ia menimbulkan tanda tanya besar tentang arah kultur politik dan intelektual kita. Beberapa buku diperlihatkan sebagai barang bukti oleh aparat, dan bahwa judul-judul yang ditunjukkan beragam nama — dari Franz Magnis-Suseno sampai karya tentang Che Guevara — sehingga wajar publik bertanya apakah tindakan itu proporsional.
Rinciannya penting karena dari sana tersusun narasi resmi: buku-buku itu “diduga” memuat paham yang memicu tindakan anarkis. Namun daftar buku yang disita, sebagaimana dilaporkan media, menunjukkan spektrum yang jauh lebih luas—karya filsafat, esai politik, dokumentasi sejarah, sampai teks teori revolusi—jenis bacaan yang secara wajar ditemukan pada rak buku mahasiswa, aktivis, atau kolektor politik. Mengonflasi keberadaan teks dengan niat melakukan tindakan kriminal adalah penyederhanaan berbahaya; dalam praktiknya, buku adalah alat berpikir — bukan senjata — dan kepemilikannya seharusnya tidak otomatis menjadi bukti kriminalitas tanpa adanya nexus yang kuat antara materi tersebut dan tindakan yang nyata. Laporan-laporan media yang menginventarisasi judul-judul yang disita memperlihatkan betapa beraneka rupa bahan bacaan itu.
Pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Kapolda — “kalau dibaca ya boleh-boleh saja, asal jangan dipraktikkan” — harus dibaca sebagai lebih dari sekadar upaya menenangkan publik. Secara retoris, ia memisahkan membaca dari tindakan; secara praktis, pernyataan itu membuka ruang interpretasi yang jauh: bila membaca sesuatu boleh tetapi “mempraktikkannya” dilarang, siapa yang menentukan kapan memahami sebuah gagasan telah berubah menjadi praktik yang dilarang? Klaim seperti ini rentan dipakai sebagai alat penjeratan: setiap bentuk studi, diskusi, atau pengajaran bisa dinilai “mendorong” praktik yang dilarang jika aparat memilih untuk membaca teks secara selektif dan instrumental. Pernyataan semacam ini memang muncul dalam laporan dan respons resmi kepolisian, dan menjadi inti dari kontroversi: apakah negara sedang mengatur tindakan atau mengatur pikiran?
Untuk menilai tindakan penyitaan secara lebih sistematis, kita perlu melihat konteks yang lebih luas: kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik di Indonesia tidaklah statis. Laporan-laporan internasional menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan terhadap penyempitan ruang diskusi publik dalam beberapa tahun terakhir—di mana aspek-aspek kebebasan berekspresi, kebebasan media, dan kebebasan akademik mengalami tekanan. Lembaga pengukuran demokrasi internasional mencatat bahwa kebebasan berekspresi termasuk salah satu indikator yang paling terpengaruh oleh proses autokratisasi global dalam beberapa tahun terakhir; di tingkat domestik, berbagai kasus kriminalisasi terhadap pengkritik, intervensi dalam kampus, dan pembatasan diskusi publik juga tercatat. Maka penyitaan buku tidak boleh dilihat sebagai peristiwa terisolasi; ia harus dilihat sebagai bagian dari pola yang lebih luas, di mana ruang wacana publik semakin terkelarkan.
Argumen historis memperkaya pemahaman kita tentang kenapa penyitaan buku memicu reaksi emosional yang kuat. Indonesia memiliki memori panjang soal pembredelan karya—khususnya pada masa Orde Baru—di mana larangan dan kriminalisasi terhadap karya tertentu menjadi alat politik untuk membungkam oposisi dan mengontrol narasi sejarah serta identitas nasional. Catatan lembaga-lembaga hak asasi dan studi sejarah memperlihatkan bahwa pembatasan terhadap karya sastra dan tekstual tidak hanya mengekang kreativitas, tetapi juga merusak kultur intelektual jangka panjang, menghasilkan masyarakat yang lebih takut mempertanyakan dan menganalisis. Pengalaman itu mestinya menjadi peringatan: ketika negara cepat menandai teks sebagai “berbahaya”, bukan hanya kebebasan individu yang terganggu, tetapi kapasitas kolektif kita untuk berpikir kritis dan membangun kebijakan publik yang lebih baik ikut terkikis.
Secara konstitusional, hak untuk menyampaikan dan menerima gagasan dilindungi. UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; inilah kerangka dasar yang seharusnya menjadi rujukan saat negara merespons tantangan keamanan yang muncul dari demonstrasi ataupun aksi massa. Jaminan konstitusional itu tidak absolut—negara memang boleh mengatur demi ketertiban umum—tetapi aturan pembatasannya harus jelas, proporsional, dan berdasarkan hukum yang dapat diuji di muka pengadilan. Jika aparat negara mengambil langkah yang tampak seperti pembatasan luas terhadap akses literatur tanpa proses hukum yang transparan dan pembuktian nexus antara teks dan tindak pidana, maka tindakan tersebut berisiko melampaui batas konstitusional dan berubah menjadi sensor terselubung.
Apa ruang legitimasi aparat dalam konteks ini? Tentu ada: polisi punya kewenangan untuk mengumpulkan barang bukti bila ada dugaan keterkaitan langsung antara benda tersebut dan tindak pidana. Beberapa pernyataan resmi menyebut buku sebagai barang bukti dalam penyelidikan terhadap kerusuhan akhir Agustus; pemerintah dan aparat menegaskan keprihatinan terhadap potensi penggunaan ideologi tertentu untuk memprovokasi tindakan anarkis. Namun legitimasi prosedural mensyaratkan lebih dari sekadar deklarasi politik: kepolisian harus menunjukkan keterkaitan faktual antara buku dan tindakan kriminal yang disangkakan—siapa yang membaca, konteks pembacaan, bukti komunikasi dan koordinasi yang nyata, atau pengakuan yang relevan—bukan hanya mengandalkan asosiasi ideologis. Tanpa itu, penyitaan mudah berubah menjadi praktik pencekalan yang merusak hak asasi. Laporan media menyampaikan penjelasan Polri soal alasan penyitaan, tetapi penjelasan administratif tidak menggantikan kebutuhan akan bukti hukum yang dapat diuji.
Dampaknya, terutama bagi daerah seperti Nusa Tenggara Timur, akan berlapis. Pada tingkat paling sederhana, tindakan semacam itu menimbulkan rasa takut: perpustakaan kampus, komunitas pembaca, kelompok gereja dan lembaga-lembaga pendidikan bisa menjadi lebih enggan mengadakan diskusi publik, menghadirkan pembicara kontroversial, atau memasukkan bacaan kritis dalam kurikulum. Akibatnya adalah kemiskinan wacana—masalah tata kelola, lingkungan, hak masyarakat adat, kebijakan pembangunan, yang mestinya disentuh oleh perdebatan terbuka, terpaksa diselesaikan dalam ruang sempit atau lewat jalan non-demokratis. Untuk daerah yang sedang membangun kapasitas partisipasi dan literasi politik, seperti NTT, kemunduran ruang publik ini berisiko menunda kemajuan sosial dan memperlebar jarak antara warga dan pengambil keputusan.
Oleh sebab itu, tanggapan yang sehat bukanlah membela pembakaran gagasan maupun membela pembredelan teks, melainkan menegakkan prinsip: bila ada indikasi keterkaitan antara suatu teks dan tindakan kriminal, tunjukkan bukti; bila tidak, kembalikan hak kepemilikan dan jangan jadikan literatur sebagai kambing hitam. Pers harus menuntut transparansi dalam proses penyitaan: apa dasar hukum yang digunakan, dokumentasi chain of custody bukti, dan apakah tersangka memiliki akses ke pembelaan hukum terkait kepemilikan buku tersebut. Akademisi dan perpustakaan harus bersiap membantu menjelaskan konteks karya yang disita, agar diskursus publik tidak diganggu oleh miskonsepsi atau propaganda.
Sebagai media refleksi dan advokasi, kita memiliki tanggung jawab ganda: menjaga keselamatan publik dengan melaporkan fakta, sambil melindungi ruang debat agar masyarakat tidak kehilangan kemampuan membedakan antara ide yang provokatif dan tindakan yang melanggar hukum.
Akhirnya, kita perlu mengajukan pertanyaan normatif yang sederhana namun mendesak: apakah bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjarah rak-rak bukunya sendiri demi menyingkirkan gagasan yang membuatnya tidak nyaman, atau bangsa yang mampu menanggapi perbedaan gagasan dengan argumen, penelitian, dan debat terbuka? Menyita buku mungkin meredam kebisingan sesaat; tetapi membungkam sumber gagasan mengikis kemampuan kolektif untuk merumuskan solusi jangka panjang. Bila kita menghendaki demokrasi yang matang, kita harus berani menghadapi gagasan, bukan memenjarakannya.
Pada akhirnya, rakyat yang terdidik dan bebas membacalah yang paling mampu menjaga keamanan bangsa tanpa harus menyerahkan pikirannya pada ketakutan.
Tim Redaksi