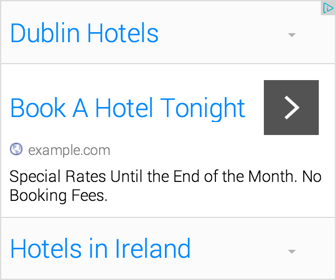KEPUTUSAN Pemerintah Indonesia menolak memberikan visa kepada atlet Israel untuk Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta bukan sekadar insiden birokratis — itu menabrak prinsip dasar olahraga internasional dan berbuah sanksi nyata dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). IOC kemudian merekomendasikan federasi internasional untuk menghentikan penyelenggaraan acara di Indonesia dan memutus pembicaraan mengenai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade. Keputusan ini secara efektif menutup jalan bagi ambisi besar Indonesia di panggung olahraga global.
Argumen pemerintah bahwa larangan itu diperlukan demi “ketertiban umum” atau sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina menempatkan kepentingan domestik di atas komitmen internasional yang sudah dijunjung ketika menerima mandat penyelenggaraan kompetisi dunia. Ketika sebuah negara menandatangani perjanjian atau bersedia menjadi tuan rumah, ada kewajiban eksplisit untuk memberikan akses nondiskriminatif kepada semua atlet yang memenuhi syarat — dan di sinilah jiwa Piagam Olimpiade dilanggar.
Dampak praktisnya langsung terasa: atlet yang telah mempersiapkan diri bertahun-tahun kehilangan kesempatan berlaga, federasi internasional menghadapi krisis penjadwalan, dan Indonesia sendiri menanggung kerugian reputasi dan ekonomi — termasuk kemungkinan dicoret dari daftar tuan rumah event besar di masa depan. IOC menunjukkan dengan tegas bahwa keputusan politik yang melanggar prinsip universal akan berimbas pada hak-hak atlet dan integritas kompetisi.
Kritik terhadap langkah pemerintah tidak berarti menafikan empati publik Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Namun, menggunakan larangan visa sebagai alat protes adalah langkah yang salah arah: ia mengorbankan warga sipil (atlet), melemahkan posisi diplomatik, dan memberi alasan kuat bagi lembaga internasional untuk menjauhkan aktivitas olahraga dari Indonesia. Keputusan ini juga menciptakan preseden berbahaya — bahwa politik domestik dapat membatalkan hak individu berdasarkan kebangsaan.
Apa yang seharusnya dilakukan Indonesia?
Pertama, menegaskan kembali komitmen pada prinsip nondiskriminasi dalam konteks olahraga internasional. Bila ingin menolak kehadiran negara tertentu atas dasar politik, maka harus siap menanggung konsekuensi penuh — termasuk kehilangan kehormatan menjadi tuan rumah.
Kedua, saluran protes yang sah adalah diplomasi dan kerja multilateral, bukan politisasi arena olahraga. Ketiga, jika Indonesia sungguh ingin mempertahankan aspirasi menjadi tuan rumah Olimpiade atau event global lain, maka perlu membangun mekanisme nasional yang menjamin akses atlet tanpa syarat diskriminatif.
Olahraga bukan ruang kosong tanpa nilai moral. Menjaga akses nondiskriminatif kepada atlet adalah wujud nyata dari nilai universal: keadilan, penghormatan, dan kesempatan yang sama. Bila Indonesia ingin tetap dihormati di dunia, ia harus belajar bahwa aksi simbolis yang terburu-buru dapat berujung pada harga politik yang mahal dan penyesalan panjang.
Tim Redaksi