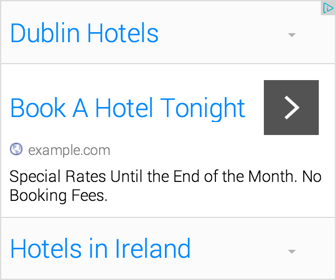Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya baru saja mengambil langkah besar dengan menempatkan dana senilai Rp200 triliun ke dalam sistem perbankan nasional, khususnya ke lima bank BUMN atau Himbara: BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Tujuannya tampak mulia: meningkatkan likuiditas, menurunkan suku bunga, dan mendorong kredit kepada sektor riil. Tetapi keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar ketika disandingkan dengan data mengejutkan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK): kredit nganggur (undisbursed loan) per Juni 2025 telah mencapai Rp2.304 triliun.
Sumber resmi menyatakan, OJK buka-bukaan terkait kredit menganggur atau fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) mencapai Rp2.304 triliun per Juni 2025. Angka itu naik dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp2.152 triliun.”
(Sumber:
Artinya, Indonesia sedang mengalami paradoks ekonomi likuiditas: uang tersedia berlimpah, tetapi tidak bergerak. Uang itu tidak hilang, hanya tidak bekerja. Dan sekarang, Rp200 triliun lagi ditambahkan ke sistem perbankan yang justru menunjukkan ketidakmampuan menyerap dana yang sudah ada. Situasi ini seperti menambah air ke kolam yang sudah penuh, berharap airnya akan mengalir ke sawah, padahal salurannya macet total.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) hanya menurunkan suku bunga menjadi 4,75 pesen yang berarti belum signifikan. Akibatnya, bank-bank enggan menyalurkan kredit ke sektor berisiko seperti UMKM atau startup karena margin terlalu kecil dan risiko gagal bayar masih tinggi. Maka pertanyaannya, apakah tambahan Rp200 triliun ini akan benar-benar masuk ke sektor riil atau hanya menjadi deposito parkir atau penopang neraca jangka pendek bank-bank pelat merah?
Kondisi ini diperparah dengan wait and see dari para pelaku usaha. Mereka enggan mengambil kredit karena tekanan daya beli masyarakat masih lemah, konsumsi stagnan, dan beban utang korporasi masih tinggi. Jadi bukan hanya bank yang enggan menyalurkan, nasabah juga enggan meminjam. Akibatnya, fenomena “kredit nganggur” menjadi cermin bahwa mesin sistem ekonomi Indonesia tengah kehilangan kepercayaan dari dalam negeri sendiri.
Seorang anggota DPR bahkan secara tegas menyampaikan: “Yang nganggur saja sudah Rp2.000-an (triliun), tambah Rp200 (triliun), kita nggak tahu nih untuk apa. Rp2.000 triliun belum bisa dimaksimalkan, masuk lagi Rp200 triliun, malah bikin beban.”
Sumber:
Dolfie Othniel Frederic Palit, Komisi XI DPR RI – https://finance.detik.com/moneter/d-8117269/ojk-buka-bukaan-soal-kredit-nganggur-yang-tembus-rp-2-000-t
Jika dana sebesar itu tetap tidak tersalurkan, maka potensi moral hazard dan opportunity cost menjadi sangat tinggi. Bayangkan, Rp200 triliun itu bisa menjadi stimulus fiskal langsung yang sangat masif bagi sektor UMKM, ketahanan pangan, atau infrastruktur dasar. Tetapi karena dikucurkan dalam bentuk penempatan likuiditas ke bank, dampaknya menjadi sangat bergantung pada apakah bank tersebut mau dan mampu menyalurkan kredit secara agresif dan tepat sasaran?
OJK memang optimis bahwa pada kuartal akhir 2025 akan terjadi percepatan realisasi kredit sesuai siklus tahunan. Tetapi optimisme tanpa reformasi struktural sistemik hanyalah harapan kosong. Tanpa adanya insentif nyata bagi sektor riil, penurunan suku bunga, serta sistem distribusi kredit yang proaktif dan terdesentralisasi, tambahan dana Rp200 triliun itu bisa jadi hanya menjadi ilusi gerak di tengah stagnasi ekonomi yang sesungguhnya. Kita lihat saja perkembangan dalam 3 – 6 bulan ke depan.
Hambatan Struktural Penyeraoan Kredit
No. 1. Permintaan Kredit yang Melemah
Data OJK menunjukkan bahwa meskipun kredit disetujui bank, pencairannya rendah. Ini menandakan permintaan aktual lemah. Dunia usaha masih ragu-ragu untuk ekspansi karena beban pajak tinggi, daya beli belum pulih, dan ketidakpastian global pasca pandemi dan konflik geopolitik. Dalam kondisi ini, bank hanya menyimpan dana tersebut tanpa penyaluran efektif.
No. 2. Suku Bunga Kredit Masih Tinggi
Meski BI Rate per September 2025 berada di 4,75 persen, suku bunga kredit UMKM masih di atas 10–12 persen. Dengan margin setipis itu, pelaku usaha tidak punya ruang manuver. Bahkan dengan dana murah sekalipun, bunga kredit tidak serta-merta turun jika biaya operasional dan risiko NPL (Non-Performing Loan) tetap tinggi.
No. 3. Bank Menjadi Terlalu Selektif
Bank saat ini lebih memilih menyalurkan kredit ke korporasi besar yang aman daripada UMKM yang penuh risiko. Maka Rp200 triliun dana murah itu berpotensi justru hanya menjadi dana parkir atau tambahan likuiditas internal, bukan untuk ekspansi kredit ke sektor produktif.
No. 4. Tidak Ada Sanksi Jika Dana Tidak Terserap
Pemerintah tidak menyiapkan mekanisme hukuman atau konsekuensi jika bank gagal menyalurkan kredit. Maka tidak ada insentif kuat untuk mengalirkan dana ke sektor yang berisiko namun berdampak luas. Bahkan bisa jadi bank menaruh dana ke SRBI (Sertifikat Rupiah Bank Indonesia) atau instrumen keuangan lain secara tidak langsung, meskipun secara eksplisit dilarang.
Skenario Optimis vs Pesimis: Apa yang Terjadi Jika Rp200 Triliun Ini Diserap atau Tidak?
Skenario Optimis – Kredit Diserap dan Dialirkan ke Sektor Riil:
Jika dana Rp200 triliun tersebut benar-benar disalurkan ke sektor produktif — UMKM, industri manufaktur, pertanian, properti rakyat (bukan spekulatif), dan infrastruktur dasar — maka efek domino ekonominya akan besar:
- Multiplier effect bisa 2–3 kali lipat. Artinya, Rp200 triliun bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi Rp400–Rp600 triliun dalam PDB.
- Setiap Rp1 triliun kredit UMKM bisa menyerap 1.500–2.000 tenaga kerja baru secara langsung dan tidak langsung.
- Penyaluran kredit ke sektor produktif akan meningkatkan demand agregat, yang kemudian menaikkan permintaan barang dan jasa, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Catatan: Dalam perhitungan BI, elasticitas kredit terhadap pertumbuhan ekonomi (credit elasticity) berkisar 0,3–0,4, artinya untuk menambah 1 persen pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pertumbuhan kredit sekitar 2,5–3 persen. Maka, jika Rp200 triliun diserap dengan kenaikan kredit sekitar 5 persen, PDB Indonesia bisa tumbuh ekstra ~1,5 persen secara tahunan.
Skenario Pesimis – Dana Hanya Mengendap atau Tidak Produktif:
Jika dana tersebut hanya “parkir” di neraca bank, maka akan terjadi:
- Crowding-out effect: dana publik malah bersaing dengan kredit swasta, membuat pasar menjadi tidak efisien.
- Moral hazard: bank merasa selalu bisa disuplai likuiditas tanpa tuntutan kinerja.
- Distorsi fiskal: Rp200 triliun itu punya opportunity cost besar — bisa digunakan untuk bansos langsung, subsidi pangan, subsidi energi, atau proyek infrastruktur rakyat.
- Risiko stagflasi: uang beredar naik, kredit tidak jalan, ekonomi stagnan → inflasi tetap naik karena sisi pasokan lemah, sedangkan permintaan tetap rendah.
Dalam jangka menengah, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan fiskal yang tidak efektif dan hanya menambah angka-angka likuiditas semu. Ini bisa memicu apa yang disebut sebagai Distrust Economy.
Perbandingan Internasional: Bagaimana Negara Lain Mengelola Dana Nganggur?
1. India
India mempunyai cadangan kredit nganggur sekitar ₹12 lakh crore (setara ±USD 144 miliar) namun berhasil mengalihkan sebagian besar kredit tersebut ke sektor agrikultur dan teknologi lewat skema subsidi terarah dan penjaminan pemerintah.
Pemerintah India menggabungkan dana publik dengan skema jaminan kredit (Credit Guarantee Fund Trust) agar bank lebih berani menyalurkan ke UMKM.
2. Vietnam
Vietnam memberikan target langsung dan wajib kepada bank untuk menyalurkan kredit dengan bunga rendah ke UMKM, dengan sistem penalti jika tidak tercapai.
Kredit ke sektor pertanian di Vietnam wajib mencapai 20 persen dari total penyaluran bank pemerintah.
3. China
China menerapkan directed lending policy — bank wajib menyalurkan ke sektor prioritas (green tech, rural industry, AI, chip, dll).
China juga menyertai stimulus moneter dengan stimulus fiskal dan pajak investasi agar uang benar-benar berputar.
Bagaimana dengan Indonesia?
Masih mengandalkan “insentif” dan “edukasi” tanpa sanksi. Penempatan Rp200 triliun hanya diiringi larangan untuk investasi di SBN, tetapi tidak disertai insentif fiskal atau aturan “wajib salur” kredit ke sektor prioritas.
Solusi Sistemik: Agar Dana Rp200 Triliun Tidak Sia-Sia
Berikut beberapa solusi konkret yang bersifat strategis sistemik:
1. Buat Kredit Wajib Salur Sektor Prioritas (Quota-Based Lending)
Tetapkan minimal 25–30 persen dari dana wajib disalurkan ke sektor-sektor produktif: UMKM, pertanian, energi baru-terbarukan, dan pendidikan. Sertai dengan insentif dan sanksi.
2. Buat Dana Penjamin Risiko Kredit
Jika bank takut NPL (Non Performing Loan) naik, pemerintah harus menyiapkan skema penjaminan (seperti Kredit Usaha Rakyat/KUR) dengan mitigasi risiko bersama, bukan hanya beban bank.
3. Integrasikan dengan Subsidi Bunga atau Pajak
Berikan insentif fiskal: bunga lebih rendah untuk sektor prioritas, atau pemotongan pajak untuk pelaku usaha yang menggunakan dana kredit untuk investasi, bukan konsumsi.
4. Laporan Publik dan Transparansi Penyaluran
Setiap bulan, OJK wajib mempublikasikan data berapa persen dana Rp200 triliun itu benar-benar disalurkan ke sektor produktif. Tanpa transparansi, potensi penyalahgunaan dan permainan angka sangat besar.
5. Koneksi Langsung ke Digital Platform UMKM
Dana Himbara harus disinergikan dengan ekosistem digital, koperasi, dan platform pembiayaan produktif berbasis teknologi agar tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar.
Analogi Bombastis: Menyiram Tanaman Plastik dengan Air Emas
Kita bisa menggambarkan situasi ini dengan analogi ekstrem:
“Pemerintah seperti menyiram tanaman plastik dengan air emas. Mewah, mahal, dan terlihat sibuk — tapi hasilnya nihil. Tanaman itu tidak bertumbuh karena ia memang palsu. Begitulah sistem keuangan Indonesia sekarang: dana besar bukan solusi jika saluran ekonomi sudah mati rasa.”
Maka pertanyaannya bukan: “Apakah kita punya uang?” Tetapi: “Apakah sistem ekonomi Indonesia mempunyai nyali dan arah untuk menggerakkan uang ke tempat yang tepat?”
Kesimpulan dan Rangkuman
Bagaimana mungkin pemerintah bisa meyakinkan publik dan pasar bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6, 7, bahkan 8 persen, jika mesin utama penggerak ekonomi — yaitu penyaluran kredit ke sektor riil — justru mengalami stagnasi strategis sistemik? Angka pertumbuhan ekonomi bukanlah mantra yang cukup dengan pengulangan, melainkan harus ditopang oleh aliran dana produktif yang nyata ke lapisan ekonomi akar rumput. Saat OJK secara terbuka mengumumkan bahwa kredit nganggur mencapai Rp2.304 triliun per Juni 2025, dan di sisi lain pemerintah kembali mengucurkan Rp200 triliun ke bank-bank pelat merah, maka publik berhak bertanya: apa sebenarnya strategi sistemik besar di balik semua ini?
Rasionalitas fiskal dan moneter dalam konteks ini seolah kehilangan arah. Jika likuiditas di sistem perbankan sudah sangat tinggi namun tidak terserap, seharusnya fokus pemerintah adalah membenahi jalur distribusi kredit dan memperkuat sisi permintaan, bukan menambah tekanan dari sisi pasokan yang justru memperbesar ketidakefisienan. Seperti menyiram pasir dengan air emas — terlihat megah, tetapi tidak menumbuhkembangkan apa-apa. Uang itu tidak hilang, tetapi juga tidak bekerja, tidak berdampak. Ia hanya mengendap sebagai angka statistik dan kebanggaan semu.
Bank-bank yang menerima dana murah ini justru menghadapi realita bahwa sektor riil enggan meminjam. Daya beli masyarakat belum pulih, risiko usaha masih tinggi, dan struktur biaya kredit tidak kompetitif. Maka wajar jika kredit tersalur tetap rendah. Bahkan ketika Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen, bunga kredit UMKM masih berada pada kisaran 10–12 persen — angka yang terlalu tinggi untuk pelaku usaha kecil menengah yang ingin bertahan, apalagi berekspansi. Di titik inilah, kita menyadari bahwa krisis kepercayaan jauh lebih besar daripada krisis likuiditas.
Ironinya, narasi ekonomi nasional terus memompa optimisme tanpa memperhitungkan hambatan struktural sistemik yang nyata. Pemerintah membanggakan cadangan devisa, indeks keuangan yang stabil, dan angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tinggi. Tetapi ketika lebih dari Rp2.300 triliun kredit tidak digunakan oleh debitur — padahal sudah disetujui bank — maka itu bukan lagi sekadar masalah teknis. Itu adalah sinyal keras bahwa ekosistem ekonomi sedang tidak sehat, bahwa mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya sedang tersumbat di semua level: dari permintaan, distribusi, hingga keberanian mengambil risiko.
Bagaimana mungkin pertumbuhan 6–8 persen bisa terjadi jika uang hanya berputar di dalam neraca bank? Jika UMKM, sektor pertanian, industri kecil, dan startup tidak memiliki akses yang mudah dan murah terhadap dana produktif, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati oleh sektor besar yang tidak inklusif. Kesenjangan akan melebar, konsumsi domestik tetap stagnan, serta efisiensi dan produktivitas nasional tidak bergerak. Dalam kerangka strategis sistemik, pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas ilusi likuiditas adalah pertumbuhan ekonomi yang rapuh.
Pemerintah semestinya belajar dari negara-negara seperti India, Vietnam, dan China, yang secara tegas menetapkan kebijakan kredit terarah (directed lending). India menggabungkan penjaminan kredit dengan alokasi sektor prioritas. Vietnam bahkan memberikan target wajib dan hukuman jika bank gagal menyalurkan ke UMKM. Sementara China memadukan stimulus moneter dan fiskal secara simultan, serta memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha produktif. Di Indonesia? Kita hanya mengandalkan himbauan moral dan kebijakan tanpa sanksi. Maka jangan heran jika bank tidak serius menyalurkan, dan uang hanya jadi alat permainan portofolio.
Masalah lain adalah tidak adanya keterbukaan data yang memadai kepada publik. Berapa dari Rp200 triliun itu yang benar-benar tersalur ke sektor produktif dalam tiga bulan pertama? Berapa yang masuk ke SRBI (Sertifikat Rupiah Bank Indonesia)? Berapa yang diserap oleh sektor UMKM? Tanpa pelaporan berkala dan akuntabilitas transparan, maka kebijakan ini akan kembali menjadi retorika fiskal yang hampa. Kebutuhan akan sistem pelaporan publik harus menjadi bagian dari reformasi struktural sistemik agar pemerintah tidak terus-menerus bermain dalam kabut.
Moral hazard pun mengintai. Ketika bank tahu bahwa likuiditas akan terus digelontorkan tanpa konsekuensi jika gagal menyalurkan, maka mereka akan cenderung memilih kenyamanan dana parkir dibanding risiko menyalurkan ke sektor yang membutuhkan pembinaan dan pendampingan. Hal ini semakin memperburuk distribusi kredit dan menambah kecenderungan ke arah stagnasi strategis sistemik jangka menengah. Akibatnya, fungsi intermediasi bank — sebagai jembatan antara surplus dana dan kebutuhan pembiayaan efisien dan produktif — berubah menjadi fungsi penyimpanan uang negara yang pasif.
Dari sisi fiskal, opportunity cost dari Rp200 triliun ini sangat besar. Uang sebesar itu jika digunakan sebagai subsidi langsung ke produksi pangan, perbaikan irigasi, digitalisasi pendidikan, atau energi terbarukan, akan menciptakan dampak langsung dan berkelanjutan bagi perekonomian rakyat. Tetapi karena formatnya adalah penempatan deposito pada bank, maka efektivitasnya sepenuhnya bergantung pada bank dan kondisi pasar — dua hal yang saat ini tidak menunjukkan optimisme tinggi.
Lebih dari sekadar keputusan moneter, kebijakan ini menggambarkan cara berpikir negara: apakah kita berani melakukan reformasi struktural sistemik atau hanya nyaman bermain angka? Jika jawaban atas krisis penyerapan kredit adalah menambah dana, maka kita tidak sedang membangun sistem ekonomi, kita sedang memelihara sistem ilusi. Maka tak berlebihan bila kita sebut ini sebagai era “ilusi pertumbuhan”, di mana semua terlihat naik di dashboard, tetapi di lapangan tak ada yang bergerak.
Pertumbuhan ekonomi sejati tidak dihasilkan dari penambahan angka input, melainkan dari efektivitas proses dan arah strategis sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi, uang adalah bahan bakar. Tetapi tanpa mesin yang efisien, bahan bakar hanya akan menguap. Indonesia hari ini ibarat mobil mewah dengan tangki penuh, tetapi bannya kempes dan sopirnya kehilangan peta. Maka sebelum bicara tentang pertumbuhan 6–8 persen, kita harus jujur mengakui bahwa sistem intermediasi kredit kita sedang rusak.
Jika pemerintah ingin membangun kepercayaan dan pertumbuhan ekonomi nyata, maka sistem kredit harus direformasi total: dari model insentifnya, dari model distribusinya, dari transparansinya, sampai dari cara berpikir sistem (strategis sistemik) para pembuat kebijakan fiskal dan moneter. Karena pada akhirnya, menyiram tanaman plastik dengan air emas bukan hanya tidak berguna, tetapi juga menyia-nyiakan sumber daya yang seharusnya menyelamatkan ekonomi rakyat. Uang itu terlalu mahal jika hanya menjadi pengisi ruang kosong di neraca bank.
Oleh: Vincent Gaspersz
Penulis adalah Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem