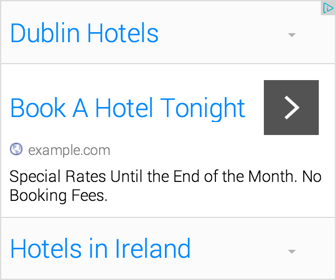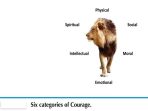Di mata publik awam, angka GDP (Gross Domestic Product) per kapita sering dianggap sebagai indikator tunggal yang mencerminkan kemakmuran suatu negara. Ketika pemerintah atau lembaga internasional menyatakan bahwa “GDP per kapita Indonesia telah mencapai USD4.925,” banyak orang awam yang langsung menyimpulkan bahwa ekonomi kita sedang baik-baik saja. Bahkan lebih baik dari negara-negara seperti Filipina, India, bahkan Jordan — yang dalam klasifikasi Bank Dunia justru sering disebut “negara miskin.” Maka muncul pertanyaan kritis: jika Indonesia punya angka GDP per kapita lebih tinggi, mengapa kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia justru terasa semakin sulit?
Itulah inti dari ilusi ekonomi makro: sebuah kesan seolah-olah kita sejahtera karena statistik ekonomi mengatakan demikian, padahal realitas sehari-hari justru membuktikan sebaliknya. GDP per kapita adalah rata-rata kasar dari seluruh nilai tambah ekonomi dibagi jumlah penduduk — tetapi tidak mencerminkan distribusi pendapatan, ketimpangan sosial, harga kebutuhan pokok, atau bahkan kemampuan daya beli riil.
Lebih tragis lagi, dengan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP), Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan untuk Upper-Middle-Income Countries (UMIC) seperti Indonesia sebesar USD8,30 per hari, atau sekitar Rp136.120 per hari, pada Kurs USD 1 = Rp16.400. Dan ketika data dikalikan dan dibandingkan dengan populasi Indonesia yang mencapai sekitar 285 juta jiwa, ditemukan fakta mengejutkan: sekitar 68 persen atau hampir 194 juta penduduk Indonesia tergolong miskin secara PPP. Artinya, walaupun secara statistik ekonomi kita “bukan negara miskin,” kondisi riil mayoritas rakyat justru mencerminkan kehidupan negara miskin.
Dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang benar-benar berdampak bagi rakyat banyak, kita tidak boleh hanya terpaku pada satu atau dua indikator statistik ekonomi yang tampak mengesankan, seperti GDP per kapita (Produk Domestik Bruto per orang). Meskipun angka ini sering dikutip oleh pejabat pemerintah atau media untuk menunjukkan bahwa ekonomi sedang bertumbuh, kenyataannya jauh lebih kompleks dari sekadar “angka rata-rata”.
Dalam rekayasa sistem ekonomi dan manajemen sistem ekonomi, pendekatan yang digunakan selalu bersifat komprehensif, strategis, dan sistemik—artinya kita harus melihat semua variabel penting secara menyeluruh, bukan sepotong-potong.
Mengandalkan satu angka seperti GDP per kapita untuk menggambarkan kesejahteraan nasional sama halnya dengan menilai kesehatan seseorang hanya dari berat badannya, tanpa melihat tekanan darah, kadar gula, detak jantung, dan riwayat penyakitnya. Angka GDP per kapita memang memberi gambaran total nilai ekonomi dibagi rata ke seluruh penduduk, tetapi ia tidak menunjukkan siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan itu. Apakah hanya kelompok 1 persen terkaya? Apakah buruh, petani, dan nelayan juga ikut merasakan? Inilah pertanyaan penting yang sering disembunyikan di balik angka statistik makro ekonomi.
Jika kita tidak mempertimbangkan distribusi pendapatan, tingkat ketimpangan ekonomi (seperti rasio Gini), akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, serta daya beli riil masyarakat, maka kita sedang terjebak dalam apa yang disebut sebagai “ilusi makroekonomi.” Ini adalah kondisi di mana data terlihat indah di atas kertas, tetapi kehidupan nyata masyarakat tetap sengsara. Kita seperti berada di negeri dongeng ekonomi, di mana kemajuan hanya hidup dalam presentasi PowerPoint para birokrat.
Ilusi ini sangat berbahaya karena dapat menyesatkan kebijakan publik. Pemerintah bisa saja mengklaim bahwa rakyat makin sejahtera hanya karena GDP per kapita naik, padahal kenyataannya harga-harga naik, gaji stagnan, dan utang rumah tangga meningkat. Para pengambil keputusan menjadi buta terhadap penderitaan rakyat karena mereka hanya melihat statistik rata-rata, bukan kondisi konkret di lapangan.
Karena itu, para ahli rekayasa sistem selalu menekankan bahwa sebuah sistem ekonomi harus dianalisis melalui berbagai parameter yang saling terhubung, bukan dipersempit pada satu angka semu. Ini seperti merancang sistem mesin industri: kita tidak hanya melihat satu tombol atau satu roda gigi, melainkan keseluruhan alur kerja, interaksi komponen, dan potensi kegagalan (failure modes) yang tersembunyi. Begitu pula dalam ekonomi—tanpa memahami sistemnya secara utuh, kita mudah tertipu oleh data yang tampak “baik” tetapi menyembunyikan kerentanan struktural sistemik.
Dengan kata lain, GDP per kapita bisa saja naik setiap tahun, tetapi jika kesenjangan makin melebar, angka pengangguran tersembunyi meningkat, dan mayoritas rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan global, maka sesungguhnya negara tersebut sedang menuju kegagalan strategis sistemik, bukan kemajuan ekonomi. Kita harus jujur dalam membaca data dan berani menolak ilusi-ilusi yang selama ini dipelihara demi pencitraan semata.
Oleh karena itu, artikel ini disusun bukan untuk menyerang pemerintah atau menyalahkan lembaga internasional, melainkan sebagai ajakan untuk melihat lebih mendalam, lebih kritis, dan lebih jujur terhadap realitas ekonomi Indonesia. Kita akan membongkar satu per satu mitos di balik indikator GDP per kapita yang selama ini sering dijadikan tolok ukur utama oleh banyak pihak, dengan menggunakan analogi sederhana, perhitungan yang mudah dipahami, dan logika awam, agar semua lapisan masyarakat—termasuk yang bukan ahli ekonomi—dapat memahami bahwa angka besar tidak selalu berarti kehidupan yang lebih baik. Lebih dari itu, artikel ini bertujuan meluruskan cara pandang publik terhadap indikator ekonomi makro, membongkar mekanisme angka statistik yang manipulatif atau menyesatkan secara strategis sistemik, serta memberikan pemahaman logis berbasis data dan kondisi nyata di lapangan, agar kita semua sebagai warga negara bisa mengambil sikap yang kritis namun tetap konstruktif dalam menilai arah pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya.
Bagian 1. Ilusi GDP Per Kapita: Mengapa Indonesia Terlihat Maju tetapi Rentan Miskin
Dalam laporan-laporan resmi, Indonesia sering dibanggakan sebagai negara yang telah keluar dari status “negara miskin” dan masuk kategori Upper-Middle-Income Country (UMIC) atau negara berpendapatan menengah atas menurut klasifikasi Bank Dunia. Namun di balik klaim itu, terdapat sebuah ironi tajam: Indonesia memiliki GDP per kapita yang hanya sedikit lebih tinggi dari Jordan (Yordania), sebuah negara yang justru oleh banyak lembaga internasional masih digolongkan sebagai negara rentan atau mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa GDP per kapita Indonesia tahun 2024 adalah sebesar USD4.925, sementara Jordan (Yordania) hanya USD4.618. Angka ini seolah-olah menempatkan Indonesia pada posisi yang “lebih maju” dari Jordan. Tetapi, apakah benar rakyat Indonesia hidup lebih sejahtera dari rakyat Jordan hanya karena angka itu?
GDP per kapita hanyalah rata-rata pembagian total output ekonomi sebuah negara terhadap jumlah penduduknya. Ia tidak menunjukkan siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi sering kali tidak merata. Segelintir elite menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara sebagian besar rakyat Indonesia justru hidup dalam situasi rentan miskin—baik secara penghasilan, akses layanan dasar, maupun daya tahan terhadap guncangan ekonomi. Angka GDP per kapita sebesar USD4.925 itu menjadi ilusi, karena tidak mencerminkan kondisi nyata mayoritas rakyat Indonesia. Angka statistik rata-rata tidak berarti adil. Angka rata-rata tidak berarti merata.
Bandingkan dengan Jordan, yang meskipun secara angka GDP per kapita lebih rendah dari Indonesia, memiliki sistem perlindungan sosial yang lebih tertata dan pemerataan akses publik yang relatif lebih merata. Bahkan beberapa indikator sosial seperti literasi, akses air bersih, dan pelayanan kesehatan dasar menunjukkan bahwa Jordan lebih konsisten dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Ironinya, Indonesia masih dihadapkan pada krisis layanan dasar di banyak wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Di Papua, NTT, Maluku, dan sebagian Kalimantan serta Sulawesi, masyarakat masih hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan, jauh dari angka USD4.925 per kapita yang diklaim.
Lebih lanjut, tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia tergolong tinggi. Indeks Gini Indonesia bertahan di kisaran 0,38–0,40, yang artinya kekayaan dan pendapatan terdistribusi secara timpang. Bahkan Bank Dunia sendiri pernah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir sebagian besar dinikmati oleh 20 persen orang terkaya. Artinya, angka GDP per kapita itu sangat mungkin “terdistorsi” oleh akumulasi kekayaan di segelintir orang saja, bukan gambaran umum kondisi masyarakat. Di sisi lain, pengeluaran rumah tangga kelas bawah semakin terbebani oleh inflasi, pajak, dan utang konsumtif.
Jika GDP per kapita dihitung sebagai indikator tunggal untuk menentukan apakah sebuah negara itu “maju” atau “sejahtera”, maka itu adalah kesalahan fatal dalam berpikir ekonomi makro. GDP tidak melihat kualitas hidup, tidak melihat ketimpangan, tidak melihat akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan rasa aman. Dalam banyak desa di Indonesia, masih banyak anak-anak yang harus berjalan kaki puluhan kilometer ke sekolah, rumah-rumah tanpa sanitasi layak, dan warga yang bergantung pada pinjaman harian dengan bunga mencekik untuk sekadar makan hari ini. Apakah semua itu sepadan dengan klaim “upper-middle income country (UMIC)”?
Masalahnya tidak berhenti di sana. Ketergantungan terhadap angka GDP membuat pemerintah cenderung berfokus pada capaian-capaian makro ekonomi yang bisa diklaim dalam forum internasional, tetapi tidak menyentuh akar struktural persoalan ekonomi domestik. Dana infrastruktur terus-menerus digelontorkan, tetapi tanpa distribusi yang adil dan pemerataan dampak. Padahal, jika pendekatan yang digunakan adalah pembangunan berbasis kesejahteraan rakyat, maka prioritasnya harus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan, bukan sekadar pencapaian angka makro ekonomi seperti GDP per kapita yang menyesatkan itu.
Jordan, meskipun dihadapkan pada banyak tantangan termasuk konflik regional, keterbatasan sumber daya alam, dan keterbatasan fiskal, tetap menjaga komitmen terhadap sistem distribusi sosial yang lebih adil. Sementara itu, Indonesia justru terjebak dalam kebijakan fiskal yang kontradiktif: menaikkan pajak rakyat miskin, membatasi subsidi dasar, tetapi memberi insentif besar bagi konglomerat dan proyek mercusuar. Hal ini memperparah kesenjangan dan menciptakan jurang sosial yang menganga, yang tidak tampak dalam angka GDP per kapita.
Oleh karena itu, angka USD4.925 bukanlah representasi kemajuan ekonomi, melainkan sebuah ilusi—sebuah angka kosmetik yang menutupi wajah kemiskinan struktural Indonesia. Kita tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik angka itu dan mengabaikan kenyataan bahwa mayoritas rakyat Indonesia tidak merasakan dampak nyata dari pertumbuhan ekonomi. Inilah sebabnya mengapa kita harus mulai mempertanyakan indikator-indikator klasik seperti GDP per kapita, dan menggantinya dengan ukuran-ukuran kesejahteraan yang lebih inklusif, lebih manusiawi, dan lebih mencerminkan realitas hidup mayoritas rakyat.
Bagian 2. Indonesia dan Kutukan Negara Perangkap Pendapatan Menengah (Middle-Income Trap)
Setelah lebih dari dua dekade menikmati status sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia kini menghadapi tantangan struktural yang jauh lebih kompleks daripada sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Dunia internasional, termasuk Bank Dunia dan lembaga keuangan multilateral lainnya, sering menggunakan kategori Low-Income, Lower-Middle-Income, Upper-Middle-Income, dan High-Income Countries berdasarkan PNB (Produk Nasional Bruto) atau Gross National Income (GNI) per kapita dalam current US dollar.
Indonesia sendiri telah masuk dalam kelompok Upper-Middle-Income Countries (UMIC) sejak 2020, namun posisi ini tidak stabil. Indonesia sempat turun kembali menjadi Lower-Middle-Income pada tahun 2021 akibat dampak pandemi, sebelum akhirnya kembali ke UMIC berdasarkan pemutakhiran data terbaru. Namun apakah status ini mencerminkan fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan?
Istilah middle-income trap pertama kali diperkenalkan oleh Bank Dunia untuk menggambarkan fenomena negara-negara yang berhasil keluar dari kategori negara miskin, tetapi gagal menjadi negara maju. Mereka terjebak dalam pendapatan menengah selama puluhan tahun, tidak mampu bersaing dengan negara-negara berbiaya murah dalam hal produksi, dan juga tidak cukup inovatif atau produktif untuk bersaing dengan negara-negara berteknologi tinggi. Indonesia menunjukkan sebagian besar ciri-ciri negara yang terperangkap dalam situasi ini.
Salah satu indikator utama dari middle-income trap adalah stagnasi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi setiap tahun, pertumbuhan ini sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas mentah yang volatil. Sektor manufaktur, yang seharusnya menjadi motor utama industrialisasi dan penciptaan nilai tambah, justru mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dalam dua dekade terakhir. Tanpa lompatan signifikan dalam inovasi, digitalisasi, dan penguatan rantai nilai industri, Indonesia hanya akan mengalami pertumbuhan yang bersifat “ekstensif” dan bukan “intensif”.
Permasalahan lain yang mengunci Indonesia dalam middle-income trap adalah rendahnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Laporan PISA (Programme for International Student Assessment) secara konsisten menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam hal literasi membaca, matematika, dan sains. Ironisnya, ini terjadi di tengah pertumbuhan anggaran pendidikan yang terus-menerus meningkat. Ini mengindikasikan bahwa bukan hanya soal besaran dana, tetapi bagaimana dana tersebut digunakan — dalam hal ini, struktur kelembagaan, efektivitas kurikulum, serta kapasitas guru masih menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Lebih lanjut, tingkat investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) Indonesia masih jauh di bawah negara-negara pesaing. Menurut data UNESCO, pengeluaran Indonesia untuk R&D hanya sekitar 0,2 persen dari PDB, sangat kecil dibandingkan dengan Korea Selatan (lebih dari 4 persen), atau bahkan Vietnam yang telah melampaui angka 1 persen. Tanpa dukungan kuat terhadap inovasi, Indonesia akan terus-menerus menjadi negara produsen bahan mentah dan pasar konsumen, bukan produsen teknologi dan pemimpin pasar.
Ketimpangan sosial dan ekonomi juga memperparah jebakan ini. Gini ratio Indonesia masih di atas angka 0,38, yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang signifikan. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok ekonomi atas, sedangkan masyarakat bawah tidak merasakan peningkatan kualitas hidup yang sepadan. Urbanisasi yang tidak terkendali, krisis perumahan terjangkau, dan tingginya biaya pendidikan serta kesehatan semakin mempersempit jalan keluar dari jebakan ini.
Tidak kalah penting, Indonesia belum mampu membangun birokrasi dan tata kelola yang efisien dan bebas korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia stagnan dalam kisaran 33–38 dari skala 0–100, memperlihatkan rendahnya kepercayaan terhadap sistem institusi publik. Padahal, birokrasi yang bersih dan efisien adalah prasyarat penting bagi negara-negara yang ingin meloncat dari middle-income menuju high-income.
Dengan semua realitas ini, kita harus menyadari bahwa middle-income trap bukan sekadar isu akademik atau jargon internasional, tetapi ancaman nyata bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia. Tanpa keberanian untuk melakukan reformasi struktural dalam pendidikan, birokrasi, industrialisasi, dan redistribusi kesejahteraan, Indonesia hanya akan menjadi negara besar dengan potensi besar, namun tanpa arah dan tanpa pencapaian nyata dalam kesejahteraan rakyatnya. Kita tidak boleh terlena dengan angka GDP per kapita semata, karena angka itu bisa menipu jika tidak dibarengi dengan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Bagian 3: Menghitung Ilusi Kemakmuran: Ketika USD4.925 (GDP Per Kapita) per Tahun Tak Berarti Sejahtera
Banyak orang mengira bahwa angka GDP per kapita (Gross Domestic Product per capita) sebesar USD4.925 artinya setiap warga Indonesia memiliki pendapatan sebesar itu dalam satu tahun. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. GDP per kapita hanyalah pembagian nilai total produk domestik bruto (yaitu semua barang dan jasa yang dihasilkan Indonesia dalam setahun) dibagi dengan jumlah penduduk. Ia tidak mencerminkan distribusi kekayaan, tidak menunjukkan apakah si kaya makin kaya atau si miskin makin menderita. Maka dari itu, mari kita uraikan perhitungan ini dengan sangat sederhana agar masyarakat awam tidak terkecoh oleh tampilan angka-angka besar yang tampaknya meyakinkan.
Kita mulai dari data Bank Dunia terbaru untuk tahun 2024: GDP per kapita Indonesia adalah USD4.925. Dengan asumsi kurs 1 USD = Rp16.400, maka kita bisa menghitung berapa nilai tersebut dalam Rupiah. Caranya: USD4.925 x Rp16.400 = Rp80.770.000 per orang per tahun.
Sekilas, angka ini memang besar. Tetapi jangan cepat tergiur. Mari kita bagi angka ini ke dalam hitungan per bulan. Jika kita bagi Rp80.770.000 dengan 12 bulan, maka:
Rp80.770.000 ÷ 12 = Rp6.730.833 per bulan. Lalu jika dibagi ke 30 hari, kita dapatkan sekitar Rp224.361 per hari.
Pertanyaannya sekarang: apakah benar setiap warga negara Indonesia mendapatkan penghasilan harian sebesar Rp224 ribu? Tentu tidak. Ini hanyalah ilusi statistik ekonomi saja. Kenyataannya, sebagian besar kekayaan itu terkonsentrasi pada kelompok minoritas orang-orang kaya dan elite bisnis. Sementara rakyat kecil, buruh harian, petani, nelayan, atau pekerja informal justru tidak menikmati “rata-rata” tersebut. Mereka hidup jauh di bawah angka itu, bahkan banyak yang hanya memperoleh kurang dari Rp50.000 per hari.
Sekarang mari kita hubungkan dengan garis kemiskinan global versi Bank Dunia. Untuk negara-negara yang masuk kategori Upper-Middle-Income Country (UMIC) atau Negara Berpendapatan Menengah Atas, seperti Indonesia saat ini, Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan sebesar USD8,30 per hari. Jika dikalikan dengan kurs Rp16.400, maka:
USD 8,30 x Rp16.400 = Rp136.120 per hari.
Artinya, setiap orang yang penghasilannya di bawah Rp136.120 per hari dianggap miskin menurut standar global untuk negara berpendapatan menengah atas. Nah, jika kita bandingkan dengan kenyataan di lapangan, mayoritas penduduk Indonesia memiliki pendapatan di bawah angka ini. Bahkan, menurut analisis berbagai lembaga internasional dan Bank Dunia, sekitar 68 persen dari total populasi Indonesia hidup dengan penghasilan di bawah standar Bank Dunia tersebut.
Dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 285 juta jiwa, maka 68 persen berarti sekitar 194 juta orang masuk dalam kategori miskin menurut standar global. Ini bukan sekadar angka; ini adalah gambaran nyata bahwa GDP per kapita sebesar USD4.925 tidak mencerminkan kesejahteraan massal. Bahkan bisa menyesatkan jika digunakan tanpa memperhatikan persebaran pendapatan.
Dengan kata lain, angka rata-rata GDP per kapita itu bersifat semu. Seperti nilai rata-rata sebuah kelas di mana satu siswa mendapat nilai 100, sementara yang lain hanya mendapat 50, lalu dikatakan nilai rata-ratanya adalah 75. Padahal mayoritas siswa justru berada di bawah nilai itu. Itulah yang terjadi di Indonesia. Angka Rp224 ribu per hari seolah menjanjikan, tetapi hanya segelintir orang yang benar-benar merasakannya. Bagi mayoritas rakyat, angka itu tidak lebih dari fatamorgana statistik ekonomi.
Inilah yang menjadi bukti kuat bahwa meskipun secara nominal GDP per kapita Indonesia lebih tinggi dari Yordania (Jordan), rakyat Indonesia lebih rentan terhadap kemiskinan struktural, karena kesenjangan pendapatan sangat tinggi dan distribusi kekayaan sangat tidak merata. Maka tidak mengherankan jika kita menemukan banyak daerah yang masih kekurangan air bersih, pendidikan berkualitas rendah, kesulitan akses layanan kesehatan dasar, dan bahkan gizi anak-anak pun masih menjadi masalah serius. Semua ini menunjukkan bahwa GDP per kapita yang tinggi tidak otomatis berarti negara tersebut telah sejahtera.
Bagian 4. Statistik Ekonomi yang Menipu: Mengapa Rata-Rata GDP Per Kapita Menyembunyikan Kesenjangan Ekonomi Nyata?”
Jika kita melihat angka GDP per kapita Indonesia sebesar USD4.925 dan mengalikannya dengan kurs Rp16.400 per USD, maka kita mendapatkan angka sekitar Rp80.770.000 per tahun per orang. Ini adalah hasil dari pembagian Produk Domestik Bruto Indonesia kepada setiap penduduk. Tetapi angka ini—meskipun terlihat besar di permukaan—sebenarnya tidak menggambarkan pendapatan aktual yang diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ia hanyalah sebuah nilai rata-rata statistik, bukan realitas distribusi pendapatan.
Ketika angka tersebut dibagi 12 bulan, maka hasilnya adalah Rp6.730.833 per bulan. Jika dibagi lagi ke dalam 30 hari, maka didapatkan angka sekitar Rp224.361 per hari. Ini menimbulkan kesan bahwa setiap warga Indonesia seolah memiliki penghasilan harian lebih dari Rp200 ribu, padahal itu hanyalah efek penghitungan aritmetika sederhana. Masalahnya adalah, rata-rata ini telah dikacaukan oleh ketimpangan distribusi pendapatan.
Dalam ilmu statistika sosial, konsep ini dikenal sebagai “mean distortion” atau penyimpangan rata-rata. Ketika segelintir orang di lapisan atas memiliki penghasilan luar biasa tinggi, maka angka rata-rata akan naik drastis, meskipun sebagian besar warga justru hidup dalam kekurangan. Ibaratnya, jika ada sepuluh orang duduk di satu warung kopi, lalu Bill Gates masuk ke dalamnya, maka secara rata-rata penghasilan orang di warung itu bisa dianggap miliarder. Tetapi tentu saja, realitasnya sangat berbeda.
Begitu pula dengan GDP per kapita. Angka Rp224 ribu per hari itu tidak mencerminkan kondisi buruh tani di Nusa Tenggara Timur yang hanya menerima Rp50.000 sehari, atau pedagang kecil di pelosok Kalimantan yang berjuang keras agar bisa membawa pulang Rp70.000 untuk menghidupi keluarga. Dalam konteks ini, statistik menjadi semacam ilusi kesejahteraan yang dipakai untuk menunjukkan kemajuan semu kepada dunia internasional—tanpa menyentuh akar masalah kemiskinan.
Inilah sebabnya kita harus lebih berhati-hati dalam memahami data makroekonomi seperti GDP per kapita. Tanpa indikator pelengkap seperti indeks ketimpangan (misalnya Gini Ratio), angka kemiskinan absolut dan relatif, serta akses terhadap layanan dasar, maka angka-angka itu bisa sangat menyesatkan. Bahkan, bisa digunakan secara politis untuk menyatakan bahwa kondisi ekonomi sudah baik, padahal kenyataan di akar rumput berkata lain.
Jika kita bandingkan dengan standar kemiskinan global dari Bank Dunia untuk Negara Berpendapatan Menengah Atas (Upper-Middle-Income Country atau UMIC), maka angka minimum untuk tidak dikategorikan miskin adalah USD 8,30 per hari. Dengan kurs Rp16.400, maka itu setara dengan Rp136.120 per hari. Artinya, siapa pun di Indonesia yang berpendapatan kurang dari Rp136.120 per hari termasuk kategori miskin menurut standar internasional.
Berdasarkan analisis berbagai lembaga global, sekitar 68 persen penduduk Indonesia hidup di bawah standar ini. Jika jumlah penduduk kita diperkirakan sekitar 285 juta jiwa, maka sekitar 194 juta orang hidup dalam kemiskinan secara definisi global, meskipun statistik resmi pemerintah Indonesia melalui BPS sering menunjukkan angka kemiskinan nasional yang jauh lebih rendah. Ini adalah konflik antara persepsi statistik makro dan realitas sosial mikro.
Dengan demikian, angka GDP per kapita yang tinggi hanyalah ilusi kemajuan, jika tidak disertai dengan distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan akses terhadap layanan publik. Tanpa reformasi mendalam terhadap struktur ekonomi dan sosial, angka-angka makro hanya akan menjadi pembenaran palsu bagi sistem ekonomi yang gagal memperjuangkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan sejati bukan soal angka, melainkan soal apakah rakyat bisa hidup dengan layak dan bermartabat di tanahnya sendiri.
Bagian 5: Menyingkap Jurang Ketimpangan: Ketika Kelas Menengah Terkikis dan Si Miskin Semakin Terpinggirkan
Dalam narasi ekonomi nasional, sering kita dengar istilah “kelas menengah bertumbuh”, seolah menjadi tanda kemajuan bangsa. Namun jika kita gali lebih mendalam, kita akan menemukan kenyataan yang jauh dari narasi tersebut. Kelas menengah Indonesia saat ini sebenarnya berada di jurang kerentanan yang dalam. Mereka bukanlah pilar ekonomi yang kokoh, melainkan segmen yang mudah tergelincir ke bawah saat terjadi krisis. Mereka hidup dengan beban cicilan, inflasi pangan, biaya pendidikan tinggi, dan ketidakpastian lapangan pekerjaan. Dalam banyak kasus, mereka hanya selangkah dari kemiskinan absolut.
Kesenjangan antara kelompok terkaya dan kelompok termiskin semakin melebar. Menurut laporan Oxfam dan berbagai lembaga riset ketimpangan global, segelintir orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan setara dengan separuh dari seluruh penduduk termiskin di negeri ini. Ini bukan hiperbola. Ketimpangan ini dapat diukur dengan Koefisien Gini—semakin mendekati angka 1, semakin timpang sebuah negara. Indonesia sudah lama terjebak di angka 0,38 hingga 0,40—angka yang menunjukkan kesenjangan cukup serius. Namun statistik ini tidak cukup merefleksikan kompleksitas ketimpangan struktural yang terjadi.
Salah satu penyebab utama dari ketimpangan ini adalah model pembangunan ekonomi yang lebih berpihak pada akumulasi modal, bukan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang dikejar-kejar dalam angka GDP tidak serta merta diikuti dengan pertumbuhan pendapatan bagi mayoritas rakyat, terutama di sektor informal, agraris, dan marjinal. Upah minimum yang tidak sebanding dengan laju inflasi, ditambah dengan beban biaya hidup perkotaan yang terus-menerus naik, membuat kelompok bawah semakin sulit untuk naik kelas. Bagi mereka, bertahan hidup pun sudah menjadi perjuangan harian.
Selain itu, akses terhadap pendidikan bermutu dan layanan kesehatan berkualitas masih sangat bergantung pada status ekonomi. Mereka yang kaya bisa membeli pendidikan terbaik dan layanan medis terbaik, baik di dalam maupun luar negeri. Sementara mayoritas rakyat masih bergantung pada fasilitas publik yang sering kali minim anggaran, sumber daya manusia, dan kualitas layanan. Ketimpangan dalam akses ini memperkuat ketimpangan ekonomi, karena pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama bagi mobilitas sosial.
Ketika kita berbicara tentang “penduduk miskin” menurut Bank Dunia (yaitu yang hidup di bawah USD8,30 atau sekitar Rp136.000 per hari), kita seolah-olah membayangkan hanya mereka yang tinggal di desa-desa terpencil. Padahal, penduduk miskin hari ini juga tinggal di tengah kota—mereka yang berprofesi sebagai sopir ojek online, buruh lepas, pekerja toko, petugas satuan pengaman (satpam), guru honorer, hingga tenaga cleaning service di gedung-gedung megah. Mereka bukan pengangguran, mereka bekerja keras, namun tetap miskin karena sistem ekonomi tidak berpihak kepada mereka.
Kondisi ini menimbulkan efek sosial yang mengkhawatirkan. Ketimpangan menciptakan rasa ketidakadilan, memicu ketegangan sosial, dan melemahkan kohesi nasional. Negara dengan ketimpangan tinggi cenderung mengalami penurunan kepercayaan publik terhadap institusi, maraknya populisme, dan konflik horizontal. Ketika masyarakat melihat bahwa kerja keras tidak lagi menjamin mobilitas sosial, maka frustrasi kolektif akan menjadi bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu.
Lebih buruk lagi, ilusi bahwa Indonesia sudah sejahtera berdasarkan angka GDP per kapita menutupi kebutuhan untuk reformasi ekonomi struktural. Ketika elite politik dan pembuat kebijakan terus-menerus menggunakan angka rata-rata nasional sebagai indikator keberhasilan, maka akar masalah tidak pernah disentuh. Padahal, yang dibutuhkan adalah reformasi strategis sistemik untuk menciptakan sistem perpajakan progresif, jaminan sosial universal, subsidi produktif, dan akses inklusif terhadap modal serta pelatihan kerja yang berkualitas.
Maka jelas bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanyalah bom waktu. Tanpa distribusi kekayaan yang adil, tanpa akses yang merata terhadap peluang ekonomi, dan tanpa perlindungan bagi kelompok rentan miskin, maka negara akan terus-menerus terjebak dalam ketimpangan struktural. Angka GDP yang tinggi tidak bisa menyelamatkan negara dari kehancuran sosial jika mayoritas rakyat hidup dalam keterbatasan ekonomi. Inilah saatnya membuka mata terhadap realitas, bukan hanya angka statistik. Karena di balik angka-angka statistik itu, ada manusia yang sedang berjuang.
Bagian 6: Ketika Bank Dunia Sendiri Mengakui — Indonesia Adalah Negara Rentan Miskin
Di tengah propaganda pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan infrastruktur, muncul sebuah kenyataan yang menggelitik nurani: bahkan lembaga sekelas Bank Dunia (World Bank) pun secara tersirat—dan dalam beberapa laporan, secara eksplisit—menyatakan bahwa Indonesia masih termasuk negara yang rentan terhadap kemiskinan massal. Pernyataan ini bukan tuduhan sepele, melainkan sebuah diagnosis makroekonomi atas struktur sosial-ekonomi yang rapuh. Meskipun klasifikasi resmi menempatkan Indonesia dalam kelompok Upper-Middle-Income Country (UMIC), kenyataan di balik angka tersebut menggambarkan potret negara dengan fondasi kesejahteraan yang goyah.
Bank Dunia menggunakan berbagai indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kerentanan, mulai dari GDP per kapita, PNB (Produk Nasional Bruto atau GNI – Gross National Income), rasio kemiskinan, hingga standar pengeluaran harian. Dalam standar UMIC, garis kemiskinan ditetapkan pada USD8,30 per hari per orang. Mengacu pada kurs konservatif Rp16.400/USD, maka angka itu setara dengan Rp136.120 per hari. Setiap orang Indonesia yang pengeluarannya per hari di bawah angka itu—baik tinggal di desa maupun di kota—secara resmi tergolong miskin dalam kacamata global.
Yang mengejutkan, analisis internal Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar 68,3 persen penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran harian di bawah ambang batas UMIC tersebut. Artinya, dari sekitar 285 juta penduduk Indonesia, lebih dari 194 juta orang dikategorikan rentan miskin secara global. Ini bukan sekadar “kemiskinan absolut” seperti yang dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan kebutuhan makanan minimum, tetapi sebuah refleksi atas kegagalan sistemik dalam menciptakan daya beli yang memadai dan kehidupan yang bermartabat.
Ironisnya, angka-angka ini seringkali tidak masuk dalam narasi kebijakan publik nasional. Pemerintah Indonesia ketika mengumumkan angka-angka statistik kemiskinan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dll lebih sering menggunakan data kemiskinan versi domestik dari BPS, yang sangat konservatif, yaitu pengeluaran sekitar Rp600 ribu per bulan atau sekitar Rp20 ribu per hari—angka yang bahkan tidak cukup untuk membeli seporsi makan bergizi.
Sementara itu, Bank Dunia memakai standar yang lebih realistis dan manusiawi, karena mempertimbangkan kebutuhan dasar hidup secara global, bukan hanya sekadar tidak kelaparan. Maka, tidak heran jika versi pemerintah menyebut kemiskinan sudah “menurun”, padahal versi Bank Dunia menyatakan sebaliknya.
Ketimpangan persepsi ini menciptakan kesenjangan dalam pembuatan kebijakan. Ketika negara merasa sudah “naik kelas”, maka urgensi reformasi strategis sistemik untuk mengatasi kemiskinan struktural menjadi berkurang. Padahal, jika realitas 194 juta warga yang hidup di bawah garis kemiskinan global ini diterima sebagai fakta, maka seharusnya seluruh strategi pembangunan dan anggaran negara difokuskan untuk menurunkan angka ini secara serius, bukan malah terjebak dalam euforia statistik ekonomi versi BPS itu. Kenaikan status UMIC semestinya menjadi beban moral, bukan medali kehormatan.
Bank Dunia sendiri sudah sejak lama memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan akan menciptakan middle income trap—jebakan negara yang bertumbuh secara nominal tetapi tidak mampu menciptakan masyarakat yang benar-benar makmur. Indonesia, menurut banyak pengamat dan ekonom global, sudah mulai menunjukkan semua gejala middle income trap klasik: konsumsi rumah tangga yang didorong utang, stagnasi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, ekspor berbasis komoditas mentah, dan ketergantungan pada subsidi serta bantuan sosial sebagai alat kontrol sosial.
Dengan situasi ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia adalah negara “semu maju” — sebuah negara yang terlihat bertumbuh dari luar, tetapi rapuh dari dalam. Bank Dunia melihat celah ini, dan melalui berbagai laporan ekonominya, mereka mengajak Indonesia untuk berfokus pada investasi jangka panjang: pendidikan berkualitas, sistem jaminan sosial universal, reformasi perpajakan progresif, dan transformasi struktural sektor informal. Namun sayangnya, nasihat ini sering kali kalah oleh kepentingan politik jangka pendek dan narasi pencitraan yang menekankan keberhasilan semu.
Maka, kita sebagai rakyat dan pemikir kritis harus berani mengatakan bahwa pengakuan Bank Dunia ini bukanlah serangan terhadap Indonesia, melainkan peringatan serius. Jangan sampai kita tertidur dalam buaian angka-angka makro yang membius, sementara rakyat di bawah semakin tergilas roda ekonomi yang tidak adil. Menerima realitas ini adalah langkah awal untuk memperbaiki arah. Tidak ada kemajuan tanpa kejujuran. Dan Bank Dunia, meskipun bukan lembaga yang sempurna, telah memberikan cermin yang seharusnya membuat kita bercermin, bukan membantah.
Kesimpulan dan Rangkuman
Rekayasa sistem ekonomi dan manajemen sistem ekonomi tidak pernah bekerja dengan melihat hanya satu atau dua indikator parsial. Mereka bekerja dengan pendekatan komprehensif strategis sistemik, karena realitas sosial-ekonomi tidak bisa direduksi menjadi angka-angka statistik tunggal seperti GDP per kapita semata. Jika kita hanya melihat GDP per kapita tanpa mempertimbangkan distribusi pendapatan, tingkat ketimpangan, akses terhadap layanan dasar, dan daya beli masyarakat, maka kita sedang jatuh ke dalam jebakan ilusi makroekonomi.
Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun GDP per kapita Indonesia tahun 2024 mencapai USD4.925, dan terlihat lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain seperti Jordan (USD4.618), hal itu tidak otomatis menandakan bahwa rakyat Indonesia hidup lebih sejahtera. Angka tersebut hanyalah rata-rata statistik, yang telah terdistorsi oleh ketimpangan distribusi kekayaan yang sangat tinggi. Di permukaan, Indonesia terlihat “naik kelas” menjadi Upper-Middle-Income Country (UMIC), tetapi di lapisan dalam, sekitar 68 persen penduduk Indonesia—sekitar 194 juta orang—masih hidup di bawah garis kemiskinan global Bank Dunia.
GDP per kapita dikalikan kurs (USD4.925 x Rp16.400) memang menghasilkan angka fantastis sekitar Rp80 juta per tahun per orang, atau Rp224 ribu per hari. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat hanya memperoleh pendapatan di bawah Rp50.000 per hari, bahkan banyak yang di bawah Rp20.000 per hari. Perhitungan ini membuat jelas bahwa angka rata-rata GDP hanyalah angka fatamorgana, yang tidak merepresentasikan kondisi riil rakyat.
Dalam bagian lain dari tulisan ini juga dibahas bagaimana Indonesia berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Negara ini tidak cukup kompetitif untuk bersaing dengan negara industri maju, tetapi juga tidak cukup efisien untuk bersaing dalam biaya produksi dengan negara miskin. Ciri-ciri middle income trap yang dimiliki Indonesia termasuk: stagnasi efisiensi dan produktivitas, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya investasi R&D, serta birokrasi yang tidak efisien dan korup.
Lebih jauh lagi, statistik rata-rata yang digunakan untuk menyampaikan keberhasilan pembangunan seringkali menyembunyikan jurang ketimpangan. Misalnya, meskipun GDP per kapita naik, tetapi Koefisien Gini Indonesia tetap tinggi (sekitar 0,38-0,40), yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Kelas menengah pun rentan miskin, dengan beban biaya hidup tinggi, utang konsumtif, dan penghasilan yang stagnan.
Bank Dunia sendiri telah menyatakan dalam berbagai laporan bahwa Indonesia tetap merupakan negara yang sangat rentan terhadap kemiskinan struktural. Mereka menggunakan standar pengeluaran harian USD8,30 sebagai batas kemiskinan untuk negara UMIC, dan mayoritas rakyat Indonesia jatuh di bawah garis ini. Artinya, Indonesia mungkin tampak maju dari luar, tetapi rapuh dari dalam.
Oleh karena itu, reformasi kebijakan ekonomi dan sosial harus dilakukan secara strategis sistemik, bukan simbolik. Pemerataan akses pendidikan, jaminan sosial universal, sistem pajak progresif, serta keberpihakan pada sektor informal dan UMKM harus menjadi prioritas utama. Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan GDP harus diarahkan untuk memperkuat daya beli rakyat, bukan sekadar mengejar angka statistik untuk laporan internasional.
Lebih dari itu, kita harus mengubah cara kita memahami pembangunan. Sejahtera bukan berarti negara punya angka GDP tinggi, tetapi ketika rakyat kecil bisa makan cukup, sekolah layak, hidup sehat, dan merasa aman dalam negara yang adil. Kita butuh paradigma baru yang tidak terjebak pada angka-angka semu, tetapi fokus pada martabat manusia dan keadilan sosial.
Rekayasa sistem ekonomi yang cerdas tidak akan membiarkan negara terjebak dalam perayaan statistik yang hampa. Ia menuntut integrasi antar sektor, keberanian menyentuh akar ketimpangan, dan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi riil, bukan sekadar kosmetika angka. Karena pada akhirnya, ekonomi bukan sekadar soal pertumbuhan, tetapi tentang siapa yang bertumbuh dan berkembang serta siapa yang tertinggal.
Oleh: Vincent Gaspersz
Penulis adalah Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem