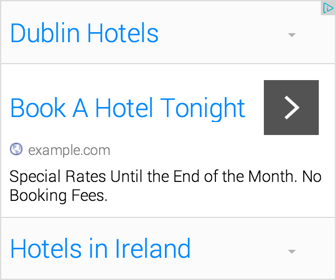Oleh: Julianus Akoit
SEJARAH selalu punya cara yang ganjil dalam menulis dirinya. Di abad pertengahan Eropa, para raja dan bangsawan kerap menarik diri ke biara atau tempat sunyi untuk “retreat”—sebuah jeda dari hiruk pikuk istana. Retret itu bukan hanya latihan rohani, tetapi juga semacam strategi: mengatur ulang napas kekuasaan, mencari legitimasi spiritual atas keputusan politik. Di Jepang, para samurai mengenal sesshin—latihan hening di kuil Zen, bukan sekadar untuk jiwa, tapi juga untuk ketajaman disiplin diri.
Di Indonesia, retret pejabat mendapat jejaknya pada masa Presiden Soeharto. Ia pernah mendorong para pejabat tinggi negara dan perwira militer untuk mengikuti semacam latihan kebatinan, meditasi, bahkan ritual doa bersama di Tapos.
Ritual ini, kemudian dihidupkan kembali oleh menantunya, Prabowo Subianto, di awal kepemimpinannya sebagai Presiden RI ke-8, beberapa bulan lalu. Kini diikuti oleh beberapa kepala daerah di Indonesia.
Retret di sini tidak hanya soal batin, tapi juga simbol kuasa—seolah penguasa adalah pemimpin rohani sekaligus politik.
Kini, berita datang dari Nusa Tenggara Timur. Para pejabat Pemprov melakukan retret di Universitas Pertahanan, Belu. Dana yang keluar: lebih dari Rp1 miliar. Angka yang tidak kecil untuk sebuah kegiatan yang, di atas kertas, dimaksudkan untuk membangun karakter kepemimpinan, memperdalam visi birokrasi, mungkin juga—entah—menyusun semacam harmoni batin di tengah keterpecahan politik lokal.
Tapi, pertanyaannya: apakah retret itu sungguh penting dan strategis?
Retret, dalam bahasa latin retrahere, berarti “menarik diri ke belakang.” Tetapi menarik diri tidak selalu berarti maju ke depan. Ia bisa jadi sekadar jeda, bisa juga pelarian. Apakah pejabat kita menarik diri dari bisingnya administrasi untuk menyelam ke dalam visi kepemimpinan yang lebih jernih? Atau hanya sekadar lari sejenak dari tekanan publik, sambil menikmati kemewahan dana negara?
Kita sudah punya program PIM—Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan Daerah—yang digelar rutin, terukur, dengan kurikulum jelas. PIM melatih para pejabat bukan hanya berteori, tetapi mengasah proyek perubahan, melatih administrasi publik dengan kerangka birokrasi yang bisa diukur. Jika sudah ada PIM, untuk apa lagi retret? Apakah retret menawarkan sesuatu yang PIM tak bisa? Ataukah ia sekadar “panggung baru” agar pejabat merasa sedang dilatih, padahal hanya mengganti seragam pelatihan dengan baju doa dan meditasi atau aktivitas sejenis?
Pertanyaan yang lebih tajam muncul: apakah ada jaminan, setelah retret, pelayanan publik jadi lebih cepat, administrasi lebih tertib, rakyat lebih terlayani? Rakyat yang berjam-jam menunggu KTP, pasien yang antre di puskesmas, guru-guru yang menanti SK—apakah mereka akan mendapat jawaban lebih cepat karena pejabatnya sudah “diremajakan” jiwanya?
Kepemimpinan, kata Max Weber, berdiri di atas etika tanggung jawab. Retret yang menghabiskan Rp1 miliar dari uang rakyat harus diuji dengan pertanyaan etika itu: apakah sebanding antara biaya yang digelontorkan dan perubahan yang dihasilkan? Etika kepemimpinan publik tidak hanya berbicara soal moral pribadi, tapi soal keadilan distribusi: apakah pantas, di tengah fiskal yang terbatas, uang itu dipakai untuk “mengheningkan cipta” di ruang nyaman, sementara jalan-jalan desa masih rusak, anak-anak sekolah masih menulis di bangku reyot?
Apalagi kita hidup di era yang menyerukan budget efficiency, efisiensi anggaran. Pemerintah pusat berulang kali mengingatkan daerah untuk menahan belanja seremonial. Lalu apa arti retret yang boros ini? Bukankah ia lebih tampak sebagai paradoks: sebuah “penghematan” yang justru diproyeksikan dalam pesta sunyi, dalam kemewahan hening yang menelan miliaran rupiah?
Di sini, retret pejabat menjelma metafora politik. Di permukaannya, ia berbicara soal doa, refleksi, perenungan. Tetapi di baliknya, bisa saja ada agenda lain: konsolidasi kekuasaan, merapatkan barisan menjelang pergeseran politik, atau bahkan menyiapkan narasi legitimasi menjelang pilkada. Politik sering berjalan diam-diam, tak selalu tampak di mimbar rapat paripurna, tapi juga bisa di ruang retret, di balik doa-doa panjang, dalam percakapan malam di antara pejabat yang saling mengukur posisi.
Maka kita bertanya dengan getir: apakah retret pejabat NTT itu sebuah perjalanan spiritual, ataukah sekadar ziarah politik yang disamarkan dengan bahasa rohani?
Seorang filsuf Yunani kuno pernah berkata, “Negara runtuh bukan karena musuh dari luar, melainkan karena mereka yang di dalam lupa untuk melayani.” Retret sejatinya adalah panggilan untuk kembali ke inti: melayani dengan jujur, bekerja dengan tulus. Tetapi bila ia hanya menjelma pesta senyap yang dibiayai pajak rakyat, maka retret itu hanyalah ironi: doa yang kehilangan jiwa, hening yang kehilangan makna.
Dan kita pun tahu, sejarah selalu menulis dirinya dengan ganjil: kadang, sebuah doa justru terdengar seperti suara uang yang jatuh ke dasar kotak kosong.***