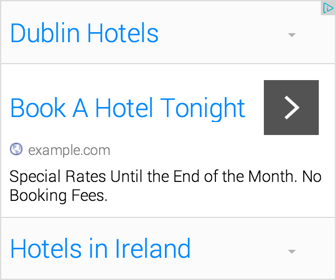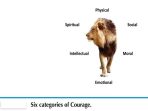Mengapa Indonesia selalu gagal karena terjebak dalam 6 persen dan mengabaikan 94 persen masalah strategis sistemik?
Di tengah kekacauan ekonomi, krisis fiskal, dan kegagalan berbagai kebijakan publik di Indonesia, perdebatan publik hampir selalu jatuh pada permainan tuding-menuding antar individu. Ketika rupiah melemah, rakyat menyalahkan Menteri Keuangan. Ketika harga beras melonjak, disalahkanlah Menteri Pertanian. Ketika subsidi dicabut, Menteri ESDM jadi sasaran. Bahkan ketika APBN bocor atau investasi tak kunjung mengalir, Gubernur BI atau Presiden dijadikan kambing hitam.
Sebagai seorang ahli rekayasa sistem dan manajemen sistem, yang telah menyelesaikan pendidikan Doktor Teknik Sistem dan Manajemen Industri di ITB (IPK = 4.0), 1991, serta memiliki pengalaman panjang sejak awal 1990-an dalam mendesain dan menerapkan sistem-sistem manajemen kinerja organisasi, saya ingin menegaskan satu prinsip yang sangat fundamental namun sering disalahpahami oleh banyak orang: “Saya tidak tertarik membahas kesalahan orang per orang”.
Mengapa? Karena jika kita membahas individu dalam konteks kegagalan sistem bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru membuka ruang bagi fitnah, subjektivitas, perdebatan personal, dan pembunuhan karakter yang merusak integritas organisasi. Lebih buruk lagi, hal ini mengalihkan perhatian dari akar persoalan sebenarnya, yaitu kerusakan dalam sistem itu sendiri.
Sejak awal karier saya di dunia industri dan organisasi, saya berpegang teguh pada prinsip ilmiah yang diajarkan oleh Dr. William Edwards Deming, seorang guru besar Statistika dan pelopor Total Quality Management (TQM) yang secara historis telah membantu para ilmuwan dan insinyur Jepang membangkitkan kembali bangsanya pasca kekalahan total dalam Perang Dunia II. Deming tidak mengajarkan mencari kambing hitam. Ia mengajarkan memahami sistem.
Salah satu ajaran Deming yang paling dikenal adalah: ““94% of problems in any organization come from the system, only 6% from the people”. Artinya, mayoritas masalah dalam organisasi, pemerintahan, maupun negara—terjadi bukan karena orangnya bodoh atau jahat, tetapi karena sistemnya salah didesain, tidak stabil, tidak dikendalikan, atau bahkan tidak pernah dievaluasi.
Pendekatan Strategis Sistemik: Dari Mikro ke Makro Ekonomi Indonesia
Oleh karena itu, dalam tulisan ini, saya akan membahas secara strategis sistemik, bagaimana prinsip-prinsip rekayasa sistem dan manajemen sistem ini harus diterapkan secara nyata dalam konteks sistem ekonomi Indonesia, baik pada level makro (sistem fiskal nasional, kebijakan moneter, kebijakan pendidikan nasional, tenaga kerja, industri, perdagangan, utang negara, subsidi, dll) maupun pada level mikro (perusahaan, UMKM, manajemen biaya, investasi SDM, efisiensi dan produktivitas operasional, dan digitalisasi).
Pembahasan ini juga akan dikaitkan langsung dengan kerangka ilmu Managerial Economics (Ekonomi Manajerial), yaitu cabang ilmu ekonomi yang mengarahkan pengambilan keputusan manajerial secara strategis, sistematis, efisien, dan berbasis data dan informasi valid.
Tujuannya adalah untuk membantu para pengambil kebijakan, akademisi, profesional, dan publik yang belum pernah belajar rekayasa sistem dan manajemen sistem, agar tidak lagi terjebak dalam paradigma lama yang selalu menyalahkan “siapa,” tetapi mampu beralih pada pertanyaan yang lebih fundamental:
“Sistem seperti apa yang menyebabkan kegagalan ini terjadi berulang-ulang?” “Apakah sistem ini memang didesain untuk gagal?”
Dalam kerangka berpikir rekayasa sistem dan manajemen sistem, kita tidak bisa memahami kegagalan sistem ekonomi Indonesia secara utuh jika tidak memiliki acuan perbandingan dari sistem ekonomi negara lain yang terbukti berhasil. Untuk itu, dua negara yang sangat relevan untuk dijadikan referensi dalam konteks ini adalah Singapura dan Korea Selatan. Kedua negara ini tidak hanya SUCCESS keluar dari krisis pasca-perang, tetapi juga mampu menata sistem ekonomi mereka secara strategis sistemik dari hulu ke hilir, dari level makro hingga mikro, dari pemerintahan pusat hingga pelaku usaha terkecil.
Singapura, sebuah negara kecil tanpa sumber daya alam, mampu menjadi pusat ekonomi dunia karena merancang sistem ekonominya secara presisi, efisien, produktif dan bebas dari korupsi. Sejak kemerdekaannya, Lee Kuan Yew membangun sistem ekonomi Singapura berdasarkan prinsip meritokrasi, penegakan hukum, efisiensi dan produktivitas fiskal, dan integrasi antara pendidikan, industri, dan teknologi. Salah satu kekuatan strategis sistemiknya adalah pembentukan Temasek Holdings dan GIC (Government of Singapore Investment Corporation) yang bertindak sebagai pengelola aset negara secara profesional, layaknya holding perusahaan kelas dunia. Tidak ada kebijakan fiskal yang dibuat tanpa analisis jangka panjang. APBN Singapura tidak mengalami defisit struktural sistemik, karena sistem pengelolaan keuangannya dibangun berdasarkan efisiensi dan produktivitas serta akuntabilitas yang tidak bisa ditawar.
Lebih dari itu, sistem ekonomi Singapura juga didukung oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan nyata dunia industri. Mereka tidak mencetak gelar akademik tanpa arah, tetapi merancang kurikulum yang langsung dikaitkan dengan strategi sistem ekonomi nasional. Setiap lulusan dipetakan ke dalam kebutuhan sektor strategis sistemik seperti bioteknologi, logistik, keuangan, dan digital economy. Dengan kata lain, sistem ekonomi mikro mereka (tingkat individu dan perusahaan) sepenuhnya disejajarkan dengan arah sistem ekonomi makro secara menyeluruh.
Di sisi lain, Korea Selatan juga merupakan contoh nyata negara yang menerapkan pendekatan rekayasa sistem dan manajemen sistem dalam membangun sistem ekonomi Korea Selatan. Pasca Perang Korea 1950-an, negara ini termasuk salah satu yang termiskin di dunia. Namun, berkat rencana jangka panjang lima tahunan yang konsisten dan terintegrasi, serta dukungan total dari pemerintah terhadap sektor industri manufaktur dan teknologi, Korea Selatan menjelma menjadi kekuatan sistem ekonomi global. Kunci keberhasilan Korea Selatan terletak pada koherensi antara kebijakan industri, pendidikan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), dan insentif fiskal untuk R&D (penelitian dan pengembangan) yang sangat tinggi—bahkan melebihi 4% dari PDB nasional per tahun.
Di bawah koordinasi Economic Planning Board (EPB) dan kemudian Ministry of Strategy and Finance, Korea Selatan menjalankan sistem ekonomi berbasis state-directed capitalism, yaitu kapitalisme yang diarahkan negara secara strategis sistemik. Pemerintah tidak bersikap pasif, tetapi juga tidak mengintervensi secara destruktif. Sebaliknya, pemerintah mengarahkan, memfasilitasi, dan merekayasa sistem ekonomi secara makro agar mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan, termasuk sektor pertanian dan industri manufaktur.
Korea Selatan membentuk chaebol (konglomerat industri besar) seperti Samsung, Hyundai, dan LG bukan sekadar untuk memperkaya segelintir elite, melainkan sebagai instrumen negara dalam membangun kapasitas produksi, ekspor, dan penguasaan teknologi global. Setiap chaebol disertakan dalam rencana lima tahunan nasional dan disupervisi secara ketat oleh pemerintah. Hubungan antara negara dan sektor swasta dibangun di atas asas kepentingan kolektif nasional.
Namun yang jarang dibahas adalah bahwa sebelum industri manufaktur Korea Selatan bertumbuh pesat, mereka terlebih dahulu memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sektor pertanian. Salah satu langkah paling revolusioner dan strategis sistemik adalah pelaksanaan land reform (reformasi agraria besar-besaran) pasca Perang Korea. Melalui kebijakan ini, tanah-tanah milik tuan tanah besar disita dan didistribusikan kepada petani kecil, sehingga lahirlah kelas menengah tani yang memiliki lahan sendiri dan insentif kuat untuk meningkatkan produksi.
Transformasi ini tidak berhenti di situ. Korea Selatan juga mendirikan Koperasi Pertanian Nasional (National Agricultural Cooperative Federation / NACF) yang dalam bahasa Korea dikenal sebagai Nonghyup (농협). Koperasi ini bukan koperasi biasa. Nonghyup dibentuk sebagai sistem ekonomi yang menguasai seluruh rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir, dan pemegang sahamnya adalah para petani itu sendiri. Mereka memiliki akses ke: Pembiayaan pertanian, Benih dan pupuk, Pelatihan teknis, Asuransi pertanian, Pengolahan hasil pertanian (value chain), Distribusi dan pemasaran produk ke ritel nasional dan ekspor.
Nonghyup menjalankan fungsi seperti bank, korporasi, distributor, dan pusat pelatihan sekaligus, dengan satu visi: memperkuat daya tawar petani dalam sistem ekonomi nasional Korea Selatan. Hasilnya sangat konkret—petani Korea Selatan bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi aktif dan pemilik saham dari sistem ekonomi yang mereka gerakkan.
Inilah contoh nyata dari sistem rekayasa ekonomi berbasis inclusive capitalism, di mana petani tidak lagi menjadi objek bantuan, tetapi menjadi subjek dan pemilik kekuatan sistem ekonomi secara kolektif.
Yang menarik, Nonghyup juga mendirikan lembaga keuangan sendiri seperti Nonghyup Bank, yang melayani masyarakat umum sekaligus memperkuat kestabilan keuangan di sektor pertanian. Mereka juga masuk ke sektor ritel dengan membangun supermarket dan outlet produk pertanian dengan label sendiri. Dengan sistem ekonomi ini, keterhubungan antara petani dan konsumen akhir tidak lagi melalui tengkulak atau rantai distribusi eksploitatif, tetapi langsung melalui konglomerasi koperasi pertanian yang mereka miliki.
Kunci keberhasilan Nonghyup dan reformasi agraria ini tidak lain adalah kekuatan sistem hukum dan politik Korea Selatan yang tegas, transparan, dan bebas dari korupsi struktural sistemik. Tidak ada kebijakan sistem ekonomi penting Korea Selatan yang dijalankan tanpa pertanggungjawaban strategis sistemik. Penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan tanpa pandang bulu, bahkan jika yang terlibat adalah direktur chaebol atau pejabat tinggi sekalipun.
Inilah yang tidak dimiliki Indonesia hari ini. Kita di Indonesia bicara koperasi, tetapi tidak membangun sistem konglomerasi koperasi. Kita bicara petani, tetapi tidak memberi mereka akses dan kepemilikan lahan pertanian. Kita bicara kedaulatan pangan, tetapi sistem ekonomi Indonesia masih tunduk pada mafia impor.
Belajar dari Korea Selatan, kita seharusnya tidak hanya membahas “mengapa petani miskin”, tetapi menyusun ulang sistem pertanian secara strategis sistemik. Indonesia perlu membentuk koperasi-koperasi petani yang sungguh-sungguh dikapitalisasi, dimodali, dilatih, dan dilindungi, bukan sekadar nama di atas kertas.
Dalam konteks ini, Dr. Deming menegaskan bahwa jika kita ingin meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta kualitas hidup petani, kita tidak bisa hanya mengubah orang, tetapi harus mengubah sistemnya. Mulai dari land reform, sistem logistik pertanian, akses permodalan, hingga keterlibatan mereka sebagai pemilik rantai pasok dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional.
Dari uraian di atas kita mengetahui bahwa baik Singapura maupun Korea Selatan sama-sama menempatkan penegakan hukum (rule of law) sebagai fondasi utama sistem ekonomi negara. Tidak ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan jika hukum bisa dibeli, jika kebijakan bisa dinegosiasikan oleh elite korup, atau jika keadilan ekonomi hanya milik segelintir kelompok. Itulah sebabnya Singapura dikenal sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi terbaik di Asia, dan Korea Selatan terus meningkatkan reformasi kelembagaannya setelah krisis Asia 1997.
Keberhasilan sistem ekonomi Singapura dan Korea Selatan tidak terletak pada individu pemimpinnya saja, melainkan pada sistem ekonomi yang dirancang untuk memaksa siapa pun yang duduk di dalamnya agar bertindak profesional, transparan, dan akuntabel. Inilah prinsip Deming yang secara nyata diterapkan di dua negara tersebut: “Every system is perfectly designed to get the results it gets.” Jika sistemnya baik, maka siapa pun yang berada dalam sistem itu akan terdorong untuk bekerja secara baik pula.
Bandingkan dengan Indonesia, yang terlalu sering menyandarkan harapan pada siapa presidennya, siapa menterinya, atau siapa gubernurnya—seolah-olah perubahan ditentukan oleh individu, bukan oleh sistem. Sementara sistem fiskal Indonesia terus-menerus dibebani oleh utang jangka panjang, APBN Indonesia digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang alih-alih investasi efisien dan produktif, serta anggaran untuk pendidikan dan riset masih sangat minim secara proporsional.
Pendidikan sistem ekonomi di Indonesia pun masih belum mengintegrasikan managerial economics dengan rekayasa sistem dan manajemen sistem. Mahasiswa dan pengambil kebijakan ketika belajar ekonomi seolah-olah sebagai teori ekonomi makro yang abstrak, terlepas dari sistem operasional ekonomi mikro yang nyata di lapangan. Tidak ada feedback loop antara kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap biaya logistik, biaya energi, efisiensi dan produktivitas industri. Tidak ada sistem digital nasional yang mampu memantau efisiensi dan produktivitas APBD dan output pembangunan di daerah. Semuanya berserakan—tidak terhubung dalam satu system of systems yang bisa dikelola secara manajemen sistem.
Itulah sebabnya kita di Indonesia perlu membuka mata dan mengalihkan lensa dari siapa yang salah menjadi sistem mana yang salah. Sistem ekonomi Indonesia hari ini sedang bergerak tanpa integrasi, tanpa arah jangka panjang yang stabil, dan tanpa penegakan hukum yang konsisten. Dalam kondisi seperti ini, mengganti orang hanya akan melahirkan kegagalan yang sama—karena sistemnya memang didesain untuk tidak menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.
Pada bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih mendalam akar penyebab kegagalan sistem ekonomi Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang diajarkan oleh Dr. William Edwards Deming—tokoh legendaris dalam rekayasa sistem dan manajemen kualitas. Pendekatan ini tidak hanya membantu kita memahami apa yang salah, tetapi lebih penting lagi: mengapa kesalahan itu terus-menerus berulang dan seperti dirancang untuk gagal.
Dengan berbekal prinsip-prinsip root cause analysis dari Deming, kita akan menguraikan bagaimana sistem ekonomi Indonesia saat ini—baik di level fiskal, pangan, pendidikan, industri, perdagangan, maupun ketenagakerjaan—telah terjebak dalam pola kesalahan struktural yang tidak pernah benar-benar dibongkar secara strategis sistemik.
Kita akan menghindari pendekatan reaktif yang hanya berfokus pada gejala permukaan, dan sebaliknya mulai membangun kerangka rekayasa sistem dan manajemen sistem ekonomi nasional Indonesia yang bersifat jangka panjang, berdaulat, dan berkelanjutan.
Dengan kata lain, kita tidak lagi mencari siapa yang bersalah, tetapi berani mengoreksi sistem ekonomi Indonesia yang salah. Kita tidak lagi berharap pada perubahan orang per orang, tetapi berkomitmen pada transformasi struktural strategi sistem. Inilah jalan menuju sistem ekonomi Indonesia yang memungkinkan keberhasilan berulang, bukan kegagalan yang terus-menerus diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya.
Bersambung ke Tulisan Kedua!
Oleh: Vincent Gaspersz
Penulis adalah Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem