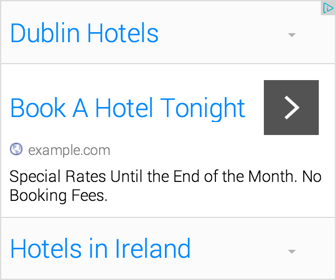Oleh: Vincent Gaspersz
Dalam sejarah panjang peradaban manusia, sistem ekonomi selalu berdiri di atas fondasi kepercayaan. Uang kertas hanya selembar kertas, kecuali masyarakat percaya bahwa negara yang menerbitkannya akan menjaga nilainya. Bank hanyalah gedung dan sistem pencatatan, kecuali masyarakat percaya bahwa uang mereka aman disimpan di sana. Bahkan kebijakan ekonomi, sekuat dan secanggih apapun, hanya akan efektif jika masyarakat percaya pada niat baik dan kapasitas intelektual para pembuat kebijakan. Namun, bagaimana jika kepercayaan itu mulai luntur? Bagaimana jika masyarakat tidak lagi yakin bahwa pemerintah mampu menjaga kestabilan, bahwa bank tidak akan membatasi akses ke uang mereka, atau bahwa uang kertas tidak akan terus-menerus kehilangan nilainya?
Inilah saat ketika Distrust Economy lahir — sebuah kondisi ketika masyarakat tidak lagi bersandar pada sistem ekonomi resmi, melainkan mulai membangun dan menjalankan ekonomi mereka sendiri, berdasarkan perlindungan diri dan logika realitas, bukan janji-janji institusi. Ini bukan bentuk perlawanan terbuka. Ini bukan revolusi berdarah. Ini adalah transisi diam-diam, di mana individu-individu mulai mengambil alih kendali penuh atas masa depan keuangan mereka. Tidak lagi percaya bukan berarti menyerang, tetapi bergeser menjauh — dari menyimpan uang ke menyimpan emas, dari menabung di bank ke mengelola aset mandiri, dari mengikuti narasi pemerintah ke menciptakan strategi sendiri.
Fenomena ini semakin terasa ketika masyarakat mulai mengurangi simpanan mereka di rekening bank dan memilih untuk mengakumulasi emas fisik. Mereka membeli emas bukan karena ingin berinvestasi, tetapi karena mereka ingin berlindung dari ketidakpastian. Ketika uang tidak lagi mampu menyimpan nilai, maka logam mulia menjadi solusi naluriah. Lebih jauh lagi, masyarakat kini dimudahkan oleh layanan seperti Brankas Emas Digital Antam (Aneka Tambang), di mana mereka bisa membeli emas secara digital — mulai dari fraksi kecil hingga gram demi gram — lalu memilih untuk mencetak fisiknya kapan saja. Tidak perlu pergi ke toko, tidak perlu menyimpan di rumah. Cukup dengan aplikasi di ponsel.
Salah satu layanan yang kini ramai digunakan adalah penyimpanan emas digital dari perusahaan logam mulia nasional. Masyarakat bisa membeli emas 0,01 gram, menyimpannya di akun mereka, lalu mencetaknya dalam bentuk fisik ketika merasa perlu. Bukan hanya satu platform, tapi berbagai lembaga resmi mulai menyediakan model serupa. Ini adalah bentuk kepercayaan baru: percaya pada emas, bukan uang kertas; percaya pada nilai benda, bukan angka di layar tabungan. Keputusan ini bukan didasarkan pada kecanggihan teknologi, tapi pada insting bertahan hidup ekonomi.
Contoh lainnya adalah masyarakat yang semakin enggan meminjam uang, walaupun suku bunga telah diturunkan oleh otoritas moneter. Bagi mereka, lebih baik menyimpan kekayaan dalam bentuk yang tak bisa “dihapus” oleh inflasi, daripada mengikat diri pada sistem pinjaman yang ujung-ujungnya bisa menjerat. Bahkan, sebagian memilih menyimpan uang tunai dalam bentuk logam mulia atau barang yang dapat ditukar langsung, dan menghindari penggunaan rekening bank secara aktif. Hal ini mencerminkan fenomena sosial yang mengakar: ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi telah mengubah perilaku ekonomi secara mendalam.
Fenomena Distrust Economy ini pernah diprediksi secara filosofis dan kritis oleh beberapa pemikir, salah satunya Nassim Nicholas Taleb, penulis buku Antifragile dan The Black Swan. Ia menyatakan bahwa sistem yang terlalu kompleks, terpusat, dan penuh asumsi kepercayaan akan rapuh menghadapi kejutan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, katanya, masyarakat yang tangguh adalah mereka yang bersandar pada sistem yang kecil, konkret, dan bisa dikendalikan sendiri. Emas, tanah, keahlian mandiri — semua itu lebih kuat dibanding saldo digital yang nilainya bergantung pada stabilitas kebijakan ekonomi yang tak bisa diprediksi.
Selain Taleb, terdapat banyak pengusaha kecil dan praktisi keuangan mandiri di berbagai pelosok yang secara naluriah telah menerapkan prinsip distrust economy tanpa pernah membaca istilahnya. Mereka tidak menyimpan uang di bank, tetapi membeli sapi, emas, beras dalam jumlah besar, atau bahkan membangun toko kecil dari hasil menabung bertahun-tahun.
Mereka tahu, jika uang hanya disimpan, nilainya akan menurun. Tetapi jika dikonversi menjadi sesuatu yang nyata yang efisien dan produktif, nilainya akan bertahan, bahkan terus-menerus meningkat. Mereka bukan ahli ekonomi, tetapi mereka memahami realitas ekonomi lebih baik daripada banyak pengambil kebijakan ekonomi.
Kita sedang menyaksikan perubahan paradigma ekonomi yang berjalan diam-diam. Sebagian masyarakat, terutama generasi muda dan pekerja sektor informal, tidak lagi percaya bahwa sistem yang sama yang menciptakan krisis akan mampu menyelamatkan mereka. Maka mereka menciptakan sistem sendiri, dalam skala kecil namun nyata. Inilah awal dari Distrust Economy. Dan kita belum melihat puncaknya.
Mengapa Kebijakan Ekonomi Tradisional Tak Lagi Efektif dalam Distrust Economy?
Di dalam sistem ekonomi konvensional, pemerintah dan bank sentral memiliki seperangkat alat untuk mengatur dan merespons kondisi sistem ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi melemah, mereka akan menurunkan suku bunga agar masyarakat terdorong untuk meminjam dan belanja. Saat inflasi tinggi, mereka akan menaikkan suku bunga agar masyarakat terdorong untuk menabung dan mengurangi konsumsi. Ketika krisis datang, pemerintah akan menggelontorkan stimulus fiskal untuk meningkatkan daya beli. Namun semua kebijakan ini asumsinya hanya akan berfungsi jika masyarakat masih percaya pada sistem ekonomi itu.
Dalam Trust Economy, asumsi dasarnya adalah masyarakat akan mengikuti sinyal dari pengambil kebijakan ekonomi. Misalnya, jika suku bunga bank turun, maka masyarakat akan tertarik untuk meminjam uang dan menjalankan usaha atau membeli rumah. Jika bunga tabungan naik, maka masyarakat akan memasukkan uangnya ke bank. Ini terlihat sederhana, tetapi semuanya sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi itu.
Salah satu gejala yang semakin mencolok dalam sistem ekonomi saat ini adalah ketika Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan, tetapi bunga kredit perbankan tetap tinggi. Tujuan awal dari penurunan suku bunga tentu agar masyarakat dan pelaku usaha terdorong untuk meminjam dana, memperluas usaha, atau meningkatkan konsumsi. Namun yang terjadi justru sebaliknya: bunga kredit tidak ikut turun signifikan, bahkan di beberapa bank justru bertahan di angka tinggi karena perbankan lebih memilih menjaga margin risiko dan mengalihkan dana mereka ke instrumen keuangan yang lebih aman dan menguntungkan.
Di saat yang sama, baik masyarakat maupun institusi keuangan justru lebih memilih menyimpan uang dengan membeli SBN (Surat Berharga Negara) yang menawarkan yield lebih tinggi dan risiko lebih rendah dibandingkan menyalurkan dana ke sektor produktif. Alih-alih mengalir ke UMKM atau industri, dana justru “parkir” di obligasi pemerintah. Akibatnya, likuiditas tampak besar secara statistik, namun tidak benar-benar mengalir ke sektor riil. Uang “beredar” di atas kertas, tetapi tidak menghidupkan mesin ekonomi masyarakat.
Fenomena ini diperparah oleh lesunya permintaan kredit dari pelaku usaha sendiri. Mereka enggan mengajukan pinjaman, meskipun bank menyatakan siap menyalurkan dana. Para pengusaha tidak percaya diri terhadap prospek bisnis, karena daya beli masyarakat rendah, biaya operasional tinggi, dan kebijakan ekonomi tidak konsisten. Akibatnya, banyak kredit yang telah disetujui tidak dicairkan, atau dana yang telah cair hanya disimpan sebagai cadangan, bukan untuk ekspansi.
Semua ini adalah sinyal nyata dari krisis kepercayaan strategis sistemik — Distrust Economy. Pelaku ekonomi, baik individu maupun lembaga, tidak lagi merespons kebijakan fiskal dan moneter sebagaimana diharapkan. Mereka tidak mempercayai arah suku bunga sebagai indikator masa depan. Mereka skeptis terhadap narasi pemulihan, dan tidak yakin bahwa sistem yang sama yang menciptakan ketidakstabilan mampu mengembalikan keseimbangan.
Dalam konteks ini, penurunan suku bunga justru tidak memicu ekspansi, tetapi memicu perburuan instrumen lindung nilai atau aset aman (safe haven) seperti SBN, logam mulia, atau bahkan aset produktif jangka panjang. Perbankan sendiri lebih memilih membeli SBN yang lebih stabil, karena risiko kredit ke sektor riil dianggap terlalu tinggi. Alhasil, fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi ekonomi lumpuh secara struktural sistemik: uang hanya berputar dalam sistem, tanpa menciptakan dampak riil bagi lapangan usaha dan kesempatan kerja.
Dampaknya sangat luas. Ketika kredit tidak tersalurkan, maka pabrik-pabrik tidak berkembang, ritel tidak bertumbuh, dan UMKM stagnan. Lapangan kerja macet, konsumsi rumah tangga datar, dan potensi pajak negara terus mengecil. Negara kehilangan efek berganda dari kebijakan fiskal maupun moneter. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan tegas: ketika kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi melemah, maka semua instrumen kebijakan menjadi tidak efektif.
Dengan demikian, fenomena seperti suku bunga turun tetapi bunga kredit tetap tinggi, dana likuid parkir di SBN, dan kredit tak terserap bukanlah sekadar masalah teknis, tetapi cerminan nyata dari Distrust Economy dalam bentuk makroekonomi. Ini bukan lagi soal kurangnya insentif, melainkan soal hilangnya kepercayaan pada efektivitas dan efisiensi sistem ekonomi. Semua pelaku ekonomi, baik besar maupun kecil, lebih memilih ‘bertahan’ daripada ‘bertumbuh dan berkembang’, lebih memilih ‘menjaga nilai’ daripada ‘mengambil risiko produktif’.
Dalam lanskap ini pula, masyarakat umum tidak tinggal diam. Mereka juga menunjukkan ekspresi Distrust Economy dalam bentuk yang berbeda namun searah. Ketika suku bunga turun, mereka tidak memperbesar konsumsi atau pinjaman, tetapi justru menyimpan kekayaan dalam bentuk aset riil seperti emas fisik atau emas digital. Mereka membeli emas bukan untuk spekulasi, tetapi untuk perlindungan nilai (hedging) dari risiko penurunan daya beli. Platform seperti Brankas Antam dan Pegadaian Digital menjadi pilihan karena mudah diakses, bisa dibeli dalam pecahan kecil, dan tidak bergantung pada stabilitas sistem perbankan.
Logika mereka pun telah berubah: bukan lagi mencari untung, melainkan menghindari rugi. Bukan lagi mengejar bunga tabungan, melainkan menjaga nilai tukar hidup. Dan ini menjadi refleksi sempurna dari bagaimana ekonomi bisa tetap berjalan tanpa kepercayaan penuh pada bank, pemerintah, atau bahkan uang kertas. Di titik inilah, Distrust Economy bukan sekadar tren pinggiran — ia telah menjadi realitas inti dari sistem ekonomi baru yang lahir dari kekecewaan, dan bertumbuh karena ketahanan.
Inilah alasan yang membuat kebijakan moneter tradisional seperti penurunan suku bunga tidak lagi efektif. Dalam konteks Tabel Perbandingan Distrust vs Trust Economy, hal ini berkaitan langsung dengan poin No. 5: “Pengaruh Suku Bunga.” Dalam Trust Economy, suku bunga adalah alat utama pengatur arah ekonomi. Dalam Distrust Economy, suku bunga tak lagi relevan karena logika ekonomi masyarakat berubah total — dari mencari untung menjadi menghindari rugi.
Kebijakan fiskal seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi belanja juga menjadi tidak terlalu efektif. Dalam sistem lama, ketika pemerintah memberikan bantuan tunai, masyarakat akan segera membelanjakan uang tersebut sehingga roda ekonomi berputar. Namun dalam Distrust Economy, bantuan tunai itu justru tidak dibelanjakan. Masyarakat memilih untuk menabung secara diam-diam, mengonversinya menjadi emas digital, atau membeli logam mulia untuk disimpan. Ini sesuai dengan poin No. 4 dan 7 pada tabel: tentang respon terhadap inflasi dan perilaku menabung.
Salah satu contoh paling nyata adalah banyaknya masyarakat yang lebih memilih membeli emas digital seberat 0,01 gram secara berkala setiap minggu, daripada menabung uang tunai di bank. Mereka menggunakan aplikasi resmi dari institusi logam mulia nasional atau platform gadai pemerintah. Ini bukan karena mereka paham teori ekonomi, melainkan karena mereka merasakan sendiri bagaimana harga-harga naik cepat sementara uang yang mereka miliki menurun nilainya.
Hal ini juga menjelaskan mengapa stimulus ke sektor formal tidak otomatis menggerakkan perekonomian. Banyak pelaku usaha mikro dan menengah yang lebih memilih untuk tidak meminjam karena tidak yakin bisa membayar cicilan jika kondisi ekonomi memburuk. Bahkan beberapa di antaranya menyatakan lebih baik memperkuat persediaan emas atau membangun usaha kecil tanpa modal pinjaman, dibanding bergantung pada pinjaman yang dikendalikan bank.
Dalam Distrust Economy, masyarakat menciptakan sistem keuangan sendiri dalam skala kecil: menyimpan emas, menyimpan bahan pokok, membangun koperasi lokal, atau barter antar komunitas. Sistem ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bertahan karena otonomi dan ketahanannya. Ini sejalan dengan poin No. 6 dan 9 dalam tabel: “Pusat Pengendali” dan “Risiko Sistemik.” Masyarakat sudah tidak bergantung pada pusat kekuasaan atau lembaga besar. Mereka menyebar risikonya melalui kendali lokal.
Lebih dari itu, dalam Distrust Economy, masyarakat tidak percaya pada narasi resmi. Ketika pemerintah menyatakan bahwa inflasi terkendali atau pertumbuhan ekonomi membaik, masyarakat justru melihat kenyataan di lapangan: harga beras naik, sewa rumah naik, biaya sekolah melonjak. Ini berkaitan dengan poin No. 11: “Sumber Kepercayaan.” Jika di masa lalu orang percaya pada data resmi, sekarang mereka percaya pada pengalaman pribadi.
Salah satu karakter paling kuat dari Distrust Economy adalah fokus pada nilai nyata, bukan angka digital. Banyak orang kini mengukur kekayaannya bukan dari saldo rekening, tetapi dari berapa gram emas yang mereka miliki, atau berapa kilogram beras dan telur yang bisa mereka simpan untuk dua bulan ke depan. Ini terlihat sangat primitif di mata sistem keuangan modern, tetapi justru itulah yang membuatnya kuat — karena tidak bergantung pada janji siapa pun.
Dalam kondisi ini, kebijakan pengumpulan pajak pun menghadapi tantangan. Ketika ekonomi rakyat berpindah ke sistem informal, barter, atau pengelolaan aset mandiri seperti emas, maka basis pajak semakin mengecil. Negara kesulitan menarik pajak dari transaksi yang tidak tercatat atau tidak melewati lembaga resmi. Ini efek jangka panjang dari Distrust Economy yang sering tidak disadari dalam perumusan kebijakan publik.
Di tengah situasi ini, masyarakat bukan sedang menolak sistem. Mereka hanya sedang menghindari sistem ekonomi yang menurut mereka tidak lagi bisa diandalkan. Dan ketika pengambil kebijakan ekonomi tidak mampu membaca sinyal ini, maka akan terjadi ketimpangan antara apa yang dianggap “fungsi” oleh negara dan apa yang dianggap “aman” oleh masyarakat umum.
Dengan demikian, Distrust Economy bukanlah gangguan sementara, melainkan cerminan dari kegagalan strategis sistemik yang telah lama diabaikan. Dan jika kebijakan ekonomi tidak mulai bertransformasi — dari pendekatan makro menuju perlindungan nilai mikro — maka jurang antara sistem ekonomi dan masyarakat umum akan semakin dalam.
Tips Praktis Konversi Penghasilan Menjadi Emas: Strategi Bertahan di Tengah Ketidakpastian
Mengubah sebagian penghasilan menjadi emas adalah langkah perlindungan nilai (hedging) yang sederhana namun sangat efektif di era Distrust Economy. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan spekulatif seperti jual beli saham, tetapi untuk menjaga daya beli jangka panjang. Emas, tidak seperti uang kertas, tidak bisa dicetak, dan telah terbukti selama ribuan tahun sebagai penyimpan nilai paling kuat saat sistem ekonomi goyah.
Langkah pertama yang paling penting adalah menentukan proporsi konversi dari penghasilan bulanan. Prinsip umum yang banyak digunakan oleh praktisi keuangan konservatif adalah mengalokasikan minimal 20% hingga 30% dari penghasilan bersih bulanan untuk emas, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Misalnya, jika seseorang berpenghasilan Rp5.000.000 per bulan, maka idealnya Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 dialokasikan untuk membeli emas secara rutin.
Langkah kedua adalah memilih metode pembelian yang sesuai. Bagi yang ingin menyimpan emas secara mandiri, bisa membeli emas fisik batangan kecil — misalnya 0,5 gram atau 1 gram. Saat ini, harga emas batangan Antam 1 gram berkisar antara Rp2.100.000 hingga Rp2.200.000, tergantung fluktuasi pasar dan biaya cetak. Bagi yang merasa belum sanggup membeli emas fisik secara utuh, kini tersedia platform emas digital seperti Brankas Antam atau Pegadaian Digital, yang memungkinkan pembelian mulai dari 0,01 gram — atau sekitar Rp21.000 hingga Rp22.000 per transaksi kecil. Ini membuka peluang konversi emas secara harian atau mingguan, bahkan untuk pekerja harian, pelaku UMKM, atau karyawan bergaji tetap dengan anggaran terbatas.
Langkah ketiga adalah menentukan waktu dan konsistensi. Jangan menunggu harga emas “turun”, karena tujuan utama membeli emas bukan untuk spekulasi, melainkan untuk melindungi daya beli jangka panjang. Gunakan pendekatan Dollar Cost Averaging (DCA), yaitu membeli secara konsisten dalam jumlah tetap, terlepas dari harga naik atau turun. Dengan cara ini, dalam jangka panjang, kita tidak terlalu terpengaruh fluktuasi harga emas.
Misalnya, seseorang dapat menetapkan alokasi Rp250.000 per minggu melalui aplikasi Pegadaian Digital atau Brankas Antam. Jika dilakukan rutin selama 52 minggu, maka dalam satu tahun ia telah mengonversi sekitar Rp13.000.000 menjadi emas. Dengan harga emas saat ini di kisaran Rp2.100.000 per gram, maka ia berhasil mengumpulkan sekitar 6 gram emas. Jumlah ini mungkin terlihat kecil, tapi dalam konteks Distrust Economy, setiap gram adalah proteksi konkret dari risiko inflasi dan pelemahan nilai uang.
Langkah keempat adalah memonitor dan mencetak emas digital jika perlu. Platform seperti Brankas Antam memberi opsi untuk mencetak fisik bila saldo sudah mencukupi, misalnya jika sudah terkumpul 5 gram atau 10 gram. Mencetak emas bisa menjadi langkah lanjutan jika ingin menyimpan sebagian emas secara fisik di rumah atau brankas pribadi. Namun bagi yang merasa lebih aman di digital, saldo tetap bisa disimpan online karena dijamin oleh institusi resmi. Perlu dicatat: meski ini berbasis institusi formal, tujuan dan logika masyarakat tetap Distrust Economy, yaitu menyimpan nilai di logam mulia, bukan uang kertas.
Sebagai contoh konkret, seorang guru honorer dengan penghasilan Rp3.500.000 per bulan merasa khawatir karena harga kebutuhan pokok terus naik, sementara pendapatannya tetap. Ia menyadari bahwa menabung uang tunai saja tidak cukup, karena nilainya terus tergerus oleh inflasi. Maka, ia mengambil keputusan sederhana namun strategis: setiap tanggal 1 dan tanggal 15, ia menyisihkan masing-masing Rp200.000 untuk membeli emas digital melalui aplikasi Pegadaian Digital.
Dengan alokasi Rp400.000 per bulan, selama satu tahun ia berhasil mengonversi Rp4.800.000 menjadi emas. Dengan asumsi harga emas digital rata-rata Rp2.100.000 per gram, maka total emas yang berhasil ia kumpulkan adalah sekitar 2,2 gram. Meskipun jumlahnya belum besar, namun emas tersebut disimpan sebagai aset tahan krisis, bukan untuk dibelanjakan.
Tahun berikutnya, saat anaknya diterima masuk SMP dan membutuhkan uang pangkal, ia tidak panik. Ia memutuskan untuk mencetak 1 gram emas digital menjadi emas fisik dan menjualnya, sementara sisa sekitar 1,2 gram tetap disimpan sebagai dana darurat. Meskipun nilainya tidak cukup untuk membayar seluruh kebutuhan sekolah, namun ia tidak mulai dari nol — dan itu membuatnya lebih tenang menghadapi situasi darurat.
Langkah kecil ini menunjukkan bahwa kemandirian finansial tidak harus dimulai dengan penghasilan besar. Kuncinya ada pada disiplin alokasi dan perlindungan nilai, bukan sekadar menabung dalam bentuk uang yang mudah tergerus waktu dan inflasi. Dalam konteks Distrust Economy, di mana banyak orang kehilangan kepercayaan pada stabilitas sistem keuangan, memiliki emas adalah bentuk perlindungan pribadi yang konkret dan realistis.
Kesimpulan dan Rangkuman
Fenomena Distrust Economy bukanlah sebuah wacana futuristik, melainkan kenyataan yang secara diam-diam telah bertumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh sistem ekonomi konvensional. Kepercayaan sebagai fondasi utama dalam sistem ekonomi — kepada pemerintah, bank, dan uang kertas (fiat money) — telah tergantikan oleh insting perlindungan diri. Ketika masyarakat tak lagi yakin bahwa institusi formal mampu menjamin kestabilan ekonomi, maka mereka mulai menciptakan mekanisme ekonomi alternatif berbasis nilai nyata, bukan janji formal.
Peralihan ini bukan hasil propaganda atau gerakan ideologis, melainkan lahir dari pengalaman hidup sehari-hari. Ketika harga sembako naik, tetapi gaji tetap; ketika uang di rekening terasa “habis secara diam-diam” karena inflasi; dan ketika bank mulai membatasi akses atau memberi bunga rendah, maka masyarakat merespons bukan dengan protes, melainkan dengan perlahan menjauh dari sistem ekonomi. Mereka membeli emas. Mereka menyimpan barang. Mereka membangun sistem kecil yang bisa mereka kendalikan sendiri.
Penggunaan emas — baik fisik maupun digital — menjadi representasi konkret dari perubahan ini. Tidak lagi hanya dimiliki oleh investor besar, kini bahkan masyarakat kecil seperti guru honorer, pedagang kaki lima, hingga pekerja harian mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli emas dalam pecahan kecil, bahkan hanya 0,01 gram sekalipun. Tujuannya bukan untuk kaya, tetapi agar tidak jatuh miskin lebih dalam akibat nilai uang yang terus-menerus menurun.
Kebijakan ekonomi konvensional yang selama ini dianggap ampuh — seperti penurunan suku bunga, bantuan tunai, atau stimulus fiskal — tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam Trust Economy, masyarakat akan menanggapi kebijakan dengan mengikuti arah yang diharapkan pemerintah. Namun dalam Distrust Economy, masyarakat tidak lagi menunggu komando, karena mereka tidak lagi percaya bahwa sistem ekonomi tersebut dapat menjamin masa depan finansial mereka. Logika ekonomi mereka telah berubah — dari mencari untung menjadi menghindari kerugian.
Sikap ini terlihat dalam penolakan terhadap pinjaman bank meski bunga rendah, dalam konversi bantuan tunai menjadi emas digital, dan dalam preferensi untuk menyimpan emas ketimbang menabung uang. Bahkan pelaku UMKM pun mulai mengandalkan modal mandiri dan tidak lagi bergantung pada kredit berbunga. Ketika dana dikucurkan oleh pemerintah ke sektor formal, hasilnya sering stagnan karena masyarakat telah memilih jalur alternatif yang mereka anggap lebih aman.
Distrust Economy juga telah merobohkan kepercayaan terhadap angka digital dan data resmi. Masyarakat kini lebih mempercayai harga beras di pasar ketimbang statistik inflasi nasional. Mereka lebih percaya berat logam mulia di tangan sendiri daripada saldo rekening yang bisa dibekukan sewaktu-waktu. Ukuran kekayaan bergeser dari “jumlah uang” menjadi “berapa gram emas”, “berapa karung beras”, atau “berapa liter minyak goreng” yang dimiliki.
Kondisi ini juga menggerus basis perpajakan negara. Ketika transaksi dilakukan secara informal, menggunakan barter, emas, atau sistem komunitas lokal, maka negara kesulitan menarik pajak. Sementara itu, jurang persepsi antara pemerintah dan masyarakat semakin dalam: negara merasa sudah menjalankan fungsi fiskal dan moneter, namun masyarakat tidak lagi merasa aman secara ekonomi. Maka terjadi benturan diam-diam antara narasi resmi dan realitas lapangan.
Namun masyarakat tidak sedang melakukan pemberontakan. Mereka hanya sedang membangun sistem baru yang lebih bisa mereka percayai, meski dalam skala kecil. Mereka menciptakan stabilitas finansial mikro yang tahan guncangan, tidak karena dijamin pemerintah, tetapi karena mereka sendiri yang mengaturnya. Emas menjadi simbol dari sistem itu — nyata, terbukti, dan tidak tergantung pada siapa yang berkuasa.
Dalam konteks inilah strategi sederhana seperti mengalokasikan 20–30 persen penghasilan untuk membeli emas menjadi sangat rasional. Bagi masyarakat kecil sekalipun, membeli 0,5 gram atau 0,01 gram per minggu menjadi bentuk konkret dari ketahanan ekonomi. Ini bukan investasi spekulatif, tapi sistem bertahan hidup. Contoh seorang guru honorer yang menyisihkan Rp400.000 per bulan untuk membeli emas, lalu menggunakannya setahun kemudian saat butuh dana sekolah anak, menunjukkan bahwa emas bukan lagi milik orang kaya — tapi alat bertahan masyarakat umum.
Contoh Nyata Distrust Economy tidak hanya terlihat dari semakin banyaknya masyarakat cerdas finansial yang beralih menyimpan emas fisik dan emas digital sebagai perlindungan nilai, tetapi juga muncul dalam bentuk-bentuk inovasi ekonomi dan sosial yang lahir karena krisis kepercayaan terhadap lembaga pusat. Hal ini terjadi karena kepercayaan terhadap negara, bank sentral, dan sistem keuangan konvensional terus-menerus melemah, baik akibat inflasi, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pembatasan akses terhadap hak finansial dasar — sehingga mendorong lahirnya sistem-sistem alternatif yang berjalan tanpa bergantung pada otoritas resmi.
Contohnya, Bitcoin diciptakan setelah krisis keuangan global 2008 sebagai bentuk protes strategis sistemik terhadap bank sentral dan uang fiat (uang kertas) yang bisa dicetak sewenang-wenang. Lalu hadir digital gold seperti Brankas Antam, Pegadaian Digital, dan Tamasia sebagai upaya masyarakat untuk menghindari risiko penyusutan nilai uang kertas. Muncul pula USDT (United States Dollar Tether) dan stablecoin, yang dirancang untuk menjaga kestabilan nilai tanpa mengandalkan mata uang negara tertentu. Dalam bidang tata kelola, lahir DAO (Decentralized Autonomous Organization) yang memungkinkan organisasi berjalan tanpa CEO atau struktur hierarkis tradisional, sebagai respons atas korporasi yang tidak transparan. Bahkan platform seperti WikiLeaks menerima donasi Bitcoin setelah diblokir oleh Visa dan PayPal — sebuah sinyal kuat bahwa ketika akses keuangan dibatasi, masyarakat mencari sistem yang tidak bisa dikendalikan secara sepihak.
Dengan semua realitas tersebut, kita tidak bisa lagi melihat Distrust Economy sebagai gangguan sementara. Ia adalah gejala strategis sistemik atas runtuhnya kepercayaan publik terhadap ekonomi konvensional. Dan jika para perancang kebijakan ekonomi tidak merespons ini dengan paradigma baru — yang menghormati pilihan logis masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri — maka sistem ekonomi secara keseluruhan akan kehilangan legitimasi dari dalam.
Oleh karena itu, arah ke depan haruslah memadukan perlindungan mikro dengan strategi makro. Negara harus belajar dari masyarakatnya, bukan sekadar mengatur dari atas. Masyarakat sudah lebih dulu beradaptasi dengan krisis — mereka membangun sistem ekonomi alternatif berbasis realitas, bukan retorika. Kini saatnya sistem ekonomi resmi membuka mata dan bergabung ke dalam logika ekonomi yang hidup dan berjalan di tingkat paling bawah: logika lindung nilai, logika emas, dan logika bertahan di tengah badai ketidakpastian.
Penulis adalah Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem